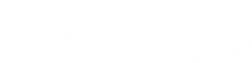MANHAJ PESANTREN

Pesantren tidak cukup hanya dipahami sebagai lembaga pendidikan biasa yang mengajarkan ilmu agama. Itu benar secara sosiologis, namun hanya pada satu sisi saja, seperti benarnya memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan pembentuk sikap religius atau kesalehan.
Jika kita telusuri sejarah dan praktik pengajaran di pesantren, yakni mengenai kurikulum keilmuan yang dipraktikkan, yang telah baku sepanjang sejarahnya, kita akan menemukan satu fakta bahwa pesantren adalah sebuah manhaj ilmu. Apa yang saya maksud dengan manhaj adalah metodologi atau cara tertentu untuk menemukan kebenaran dan kesahihan ajaran.
Kurikulum standar di pesantren—setidaknya yang saya ketahui dan ikuti ketika di pesantren—terdiri dari tiga kelompok rumpun ilmu. Pertama, ilmu-ilmu alat, yang terdiri atas ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu lughat, ilmu isytiqaq, dan ilmu ma’ani. Kelima disiplin ilmu ini sangat penting dan saling berkaitan. Ilmu nahwu (tata bahasa) mempelajari prinsip-prinsip untuk mengenali kedudukan setiap kata dalam kalimat; ilmu sharaf mempelajari prinsip-prinsip untuk mengenali pola-pola kalimat dan kondisinya; ilmu lughat adalah untuk mengetahui arti setiap kata, sebab kadang kala satu kata mengandung berbagai arti, dan terkait dengan disiplin ilmu ini adalah ilmu isytiqaq (akar kata) yang mempelajari asal-usul kata, sebab ada beberapa kata yang berasal dari dua kata yang berbeda, sehingga berbeda makna. Adapun ilmu ma’ani kedudukannya sangat penting karena dengan ilmu ma’ani susunan kalimat dapat diketahui dengan melihat maknanya.
Kedua, ilmu-ilmu metodologi dan logika. Untuk ilmu metodologi, terdiri atas disiplin ilmu ushul fiqih, ilmu tafsir, dan ilmu hadits. Mempelajari ilmu ushul fiqih sangat penting, karena dengan ilmu ini kita dapat mengambil dalil dan hukum dari suatu ayat. Dari ilmu tafsir materi yang diajarkan meliputi: ilmu bayan yang mempelajari makna zhahir dan batin (tersembunyi) serta makna kiasan dan perumpamaan, serta ilmu badi’, yaitu ilmu yang mempelajari keindahan bahasa sebagai cabang ilmu balaghah, yang juga diajarkan di pesantren. Adapun kitab pegangan yang diajarkan untuk ilmu logika adalah mantiq.
Ketiga, ilmu syariah, aqidah, dan akhlak. Disiplin ilmu syariah meliputi fiqih, hadits, dan tafsir. Disiplin hadits dan tafsir yang dimaksudkan dalam kategori ini adalah produk jadi, seperti kitab Arbain Nawawiyah dan Tafsir Jalalain misalnya. Dalam rumpun ini saya memasukkan ilmu faraid dan falaq dalam kategori syariah. Alasannya, untuk ilmu falaq karena dalam praktiknya secara spesifik diorientasikan untuk tujuan mengetahui waktu sholat. Dewasa ini ilmu falaq telah jarang sekali diajarkan di pesantren.
Itulah tiga rumpun ilmu yang terdapat dalam kurikulum standar di berbagai pesantren; sekali lagi, setidaknya itu yang berlangsung hingga saya masih mondok. Materi-materi itu adalah standar kurikulum yang diajarkan di luar bulan Ramadhan. Pada bulan Ramadhan, jenis kitab yang dibalah (dibaca/diajarkan) biasanya sangat beragam, tujuannya untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan bagi para santri.
Selain soal kurikulum, dalam tradisi keilmuan di pesantren ada hal lain yang penting dicatat, yakni adanya kontinuitas yang konstan, bahkan terjaga sedemikian rupa dalam tiga hal, yaitu: penggunaan “kitab kuning”, penerapan metode utawi-iki-iku, dan materi pengajaran yang dikaji dan dielaborasi, seluruhnya disajikan dalam visi dan nalar ilahiyah.
Kitab Kuning adalah kitab-kitab produk pemikiran dan keilmuan ulama abad pertengahan Islam, yang merentang antara tahun 800 hingga 1250 M. Sedangkan metode utawi-iki-iku adalah suatu metode pengartian atau pemaknaan kata per kata (bukan “penerjemahan” karena konotasinya berbeda) berdasarkan atau sesuai struktur dan perubahan kedudukan setiap kata, menjadi sedemikian terurai. Dengan metode itu, makna kata dan arti terdalam dari setiap kata, termasuk kandungan resonasinya, dapat diungkap secara tepat dan sempurna.
Perlu diingat bahwa kata adalah simbol bunyi, yang secara teoritis mewakili arti dari objeknya. Misalnya, kata wedus dalam bahasa Jawa adalah sebutan untuk kambing yang sudah dewasa, sedangkan cempe adalah anak kambing atau kambing yang masih kecil. Dalam bahasa Indonesia, baik yang masih kecil maupun yang besar, keduanya disebut kambing. Bahasa demikian kurang sempurna untuk bahasa ilmu pengetahuan sebab kurang memiliki akurasi objek yang direpresentasikan dalam bahasa simbol. Metode utawi-iki-iku memiliki kesempurnaan sebagai cara untuk mengurai struktur kata dan makna dalam kalimat-kalimat bahasa Arab yang memiliki karakter tersendiri dalam kompleksitas struktur kata dan kalimatnya serta pola-polanya, yang kesemuanya itu berhubungan dengan perubahan makna.
Dari bangunan kurikulum seperti telah diuraikan di atas, kita dapat mengatakan bahwa tradisi keilmuan di pesantren, baik disadari atau tidak, kesatuan dari tiga rumpun ilmu tersebut telah membentuk bangunan metodologi keilmuan yang padu dan koheren. Bangunan kurikulum yang sedemikian itu adalah manhaj (metodologi) pengetahuan Islam, yakni alat ukur yang memberi jaminan kepada para peneliti atau intelektual Muslim untuk sampai pada kebenaran yang mereka cari dan tidak tersesat pada kesalahan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kebenaran, kesahihan, dan kemurnian ajaran dan hukum-hukum Islam.
Dari semua yang telah diuraikan di atas, kiranya telah cukup gamblang dan argumentatif secara teoritis untuk dapat disimpulkan bahwa bangunan kurikulum di pesantren adalah sebuah manhaj ilmu. Bangunan kurikulum demikian bahkan tidak kita temukan pada lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia; dan bangunan kurikulum seperti itu saya sebut sebagai Manhaj Pesantren.