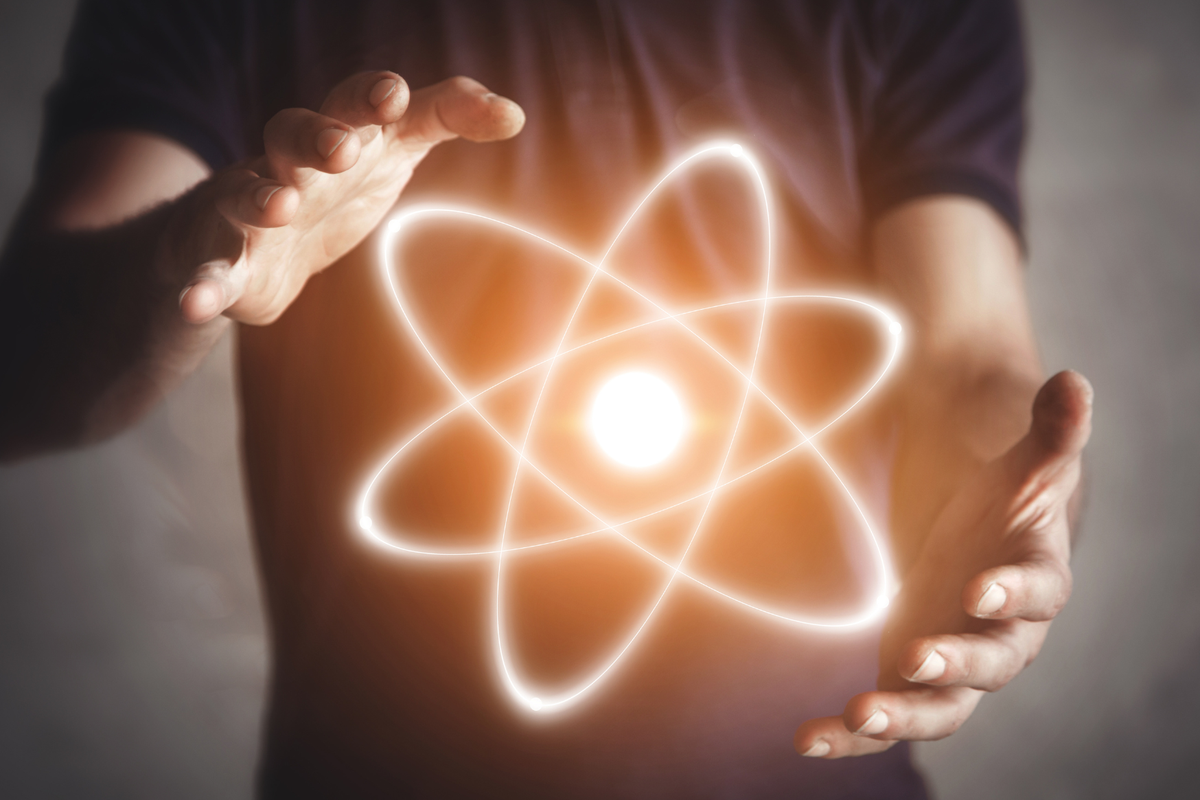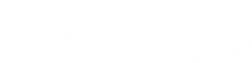Filsafat Kaum Rebahan

Kita hidup dalam zaman yang mendewakan gerak, seolah diam adalah dosa. Generasi yang memilih rebah dianggap lalai, padahal bisa jadi mereka sedang menolak panggilan dari dunia yang salah alamat. (red.)
Apa itu kebebasan? Pertanyaan yang tampak sederhana ini justru adalah jebakan. Sebab “kebebasan” tidak hadir sebagai entitas murni, tetapi selalu terperangkap dalam jaringan penandaan, dalam oposisi yang mengatur dirinya secara diam-diam: bebas/tidak bebas, aktif/pasif, subjek/objek, Tuhan/manusia. Dan dari dalam oposisi itulah, kebebasan merangkak keluar sebagai ilusi yang stabil, sebuah konsep yang mengklaim makna padahal senyatanya terus tergelincir dalam deferensi.
Ketika satu bangsa menyatakan perang atas nama kebebasan, atau seorang individu menolak tatanan sosial demi hak asasi yang disebut-sebut sebagai bawaan lahir, apakah kita benar-benar sedang berbicara tentang kebebasan? Atau justru kita tengah mengulang perintah tersembunyi dari sistem bahasa dan kekuasaan yang kita kira telah kita lawan? Kebebasan, dalam cara ini, adalah jejak yang tidak pernah sampai ke asal, sebuah trace dari struktur yang tak mungkin utuh.
Di dalam medan ini, hadir dua suara yang saling menegasikan dan sekaligus memperkukuh: Muhammad Iqbal, yang menjahit Tuhan ke dalam kain kebebasan manusia, dan Jean Paul Sartre, yang justru mencabut benang transenden itu agar manusia berdiri telanjang dalam pilihan-pilihan radikalnya.
Tapi apakah benar mereka saling bertolak belakang? Atau justru pertentangan itu sendiri merupakan konstruksi dari sistem metafisika kehadiran yang harus kita gugurkan?
Eksistensi manusia, sebagaimana akan kita lihat, bukan sesuatu yang hadir begitu saja. Maka membaca filsafat kebebasan bukanlah sekadar menafsirkan isi, tetapi membongkar perbedaan, membuka luka pada permukaan wacana, dan mempertanyakan: apakah kita pernah benar-benar bebas?
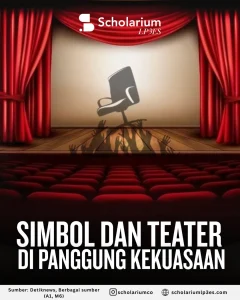
Dari Eksistensialisme Ke Rebahan(isme)
Eksistensialisme, begitu kata kamus filsafat, berasal dari akar kata existere, yang berarti keluar, muncul, berdiri di hadapan. Tapi keluar dari mana? Berdiri terhadap apa? Segala upaya definisi di sini justru menyiratkan sebuah keraguan mendasar: bahwa eksistensi, sebagai pengalaman manusia yang sadar, tak pernah hadir secara penuh. Ia selalu merupakan kehadiran yang tertunda (différance) yang menyingkap justru melalui ketersembunyian maknanya sendiri.
Eksistensialisme dikatakan menolak reduksi manusia menjadi objek. Tapi penolakan itu sendiri hanya mungkin muncul dalam sistem yang telah lebih dulu menciptakan oposisi: antara subjek dan objek, antara makna dan materialitas, antara Tuhan dan yang fana. Maka, apakah eksistensialisme adalah pembebasan, atau hanya pembalikan dari struktur metafisis yang sama?
Di sinilah, dikatakan, dua jalur berpisah: eksistensialisme teistik yang dalam nama seperti Muhammad Iqbal menempatkan Tuhan sebagai akar yang memberi makna pada diri manusia dan eksistensialisme ateistik, yang dalam suara Jean Paul Sartre memaksa manusia untuk menjadi makhluk yang dilempar ke dunia tanpa manual, tanpa makna, tanpa Tuhan.
Tapi di antara dua kutub ini, kita sebetulnya tidak sedang memilih, melainkan terjebak. Sebab Tuhan maupun ketiadaan-Nya, dalam sistem eksistensial, bekerja dengan logika yang sama, sebagai pusat yang mengatur tafsir, sebagai logos yang menentukan.
Jadi, pertanyaannya bukan: apakah manusia bebas karena Tuhan, atau karena ketiadaan Tuhan? Melainkan: apakah konsep bebas itu sendiri bukanlah produk dari sistem yang menundukkan manusia pada permainan makna yang tak pernah selesai?
Iqbal berkata: khudi –aku, diri, ego– adalah pusat dari eksistensi manusia. Tapi pusat macam apa? Ia bukan pusat yang diam dan stabil, melainkan pusat yang bergerak, membesar, memadat, menyatu menuju Khuda, sang Ego Mutlak. Sebuah puncak, ya, tapi sekaligus jurang, karena dalam kedekatan dengan Yang Mutlak, sang khudi tidak lenyap, justru menjadi sepenuhnya dirinya.
Namun di sinilah paradoks mengintai, jika khudi adalah bebas, unik, dan kreatif, mengapa ia mesti mendaki menuju yang lain, yakni Tuhan? Apakah kebebasannya bukan justru disusun oleh kebergantungannya, oleh keharusan untuk menjadi “wakil-Nya”? Maka kebebasan yang ditawarkan Iqbal bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang telah dimediasi oleh struktur teologis. Dengan kata lain, “bebas” di sini bukanlah tanpa tuan, melainkan tunduk kepada Tu(h)an. Bebas untuk menjadi alat. Alat yang sadar, tapi tetap alat.
Sebaliknya, Sartre membuka pintu ke ruangan yang kosong. Tidak ada Tuhan, tidak ada esensi yang mendahului eksistensi. Tidak ada jaminan, tidak ada penonton ilahi. Dan justru di sanalah –katanya– kebebasan dimulai. “Manusia adalah apa yang ia buat dari dirinya sendiri.” Tapi sekali lagi, apakah “dirinya” itu benar-benar ada sebelum dibuat? Apakah “dirinya” bukan juga efek dari struktur bahasa, dari wacana, dari luka kolonial dan absurditas sejarah?
Ketika Sartre berkata bahwa keberadaan Tuhan menghapus kebebasan manusia, kita sedang melihat bagaimana satu oposisi biner dijungkirbalikkan untuk memperkuat makna kebalikannya. Dalam menjungkirkan, kita sering masih berada di dalam lingkaran yang sama. Sartre menghilangkan Tuhan agar manusia menjadi pusat, tapi pusat itu tetap fiksional, karena “manusia” sendiri bukan titik awal yang stabil, melainkan hasil dari konstruksi, bukan substansi.
Maka Iqbal dan Sartre tidak benar-benar saling menegasikan. Mereka justru saling menerjemahkan satu sama lain ke dalam bahasa oposisi yang sama: kehadiran versus ketiadaan, fondasi versus kebebasan, makna versus kehampaan. Tapi dalam permainan ini, siapa yang sungguh bebas?
Ada yang mengganggu dalam narasi klasik tentang kebebasan, bahwa ia adalah milik pribadi, bahwa batasnya adalah orang lain, bahwa pertarungan utama manusia adalah menjaga agar kebebasannya tidak ditelan oleh kebebasan yang lain. Iqbal, dengan khudi-nya, membuka ruang bahwa kebebasan bukanlah medan konflik, melainkan jembatan, ia tumbuh, justru ketika diri menyadari bahwa orang lain pun memiliki keunikan dan jalan menuju Tuhan yang sama sahnya. Sedangkan Sartre, dengan posisi ekstremnya, memotret kebebasan orang lain sebagai ancaman, sebagai cermin yang menghantui: “l’enfer, c’est les autres” neraka adalah orang lain.
Tapi benarkah?
Ataukah kita selama ini terlalu percaya pada dikotomi itu, bahwa diri adalah satu dan orang lain adalah lain? Bahwa “generasi saya” adalah kuat, dan “generasi kalian” adalah lemah? Bahwa kebebasan adalah perjuangan naik tangga, bukan ketenangan duduk di lantai?
Kini kita berhadapan dengan sebuah konstruksi baru yang sedang diproduksi dan direproduksi: Generasi Z disebut juga generasi rebahan, generasi stroberi, generasi yang halus tapi gampang hancur, yang katanya hanya tahu scroll, swipe, dan streaming. Tapi siapa yang berbicara? Dan dari posisi siapa stereotip itu dinarasikan?
Apakah kita tidak sedang mengalami pengulangan bentuk yang sama: pengobjekkan orang lain agar kebebasan diri terasa lebih murni? Bukankah dengan menyebut Gen Z sebagai “pasif”, kita sedang menyusun ulang oposisi biner antara aktif/pasif, produktif/tidak produktif, berdaya/tidak berdaya dan pada akhirnya bebas/tidak bebas?
Jangan-jangan semua oposisi-oposisi itu rapuh. Barangkali, dalam diam dan keterasingannya, Generasi Z sedang menjalani bentuk kebebasan yang sama radikalnya, tapi dengan bahasa yang belum dipahami generasi sebelumnya. Barangkali mereka sedang, seperti Sartre, menghadapi absurditas dunia tanpa Tuhan dan tanpa arah; atau seperti Iqbal, mencari khudi –diri yang otentik– di tengah dunia yang dibanjiri tiruan dan algoritma.
Maka pertanyaannya bergeser: bukan apakah mereka bebas seperti yang kita pahami, tapi apakah kita bersedia mendekonstruksi pemahaman kita tentang kebebasan itu sendiri?
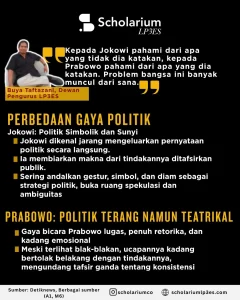
Rebahan Menuju Re(de)finisi Diri
Dalam ruang-ruang diskusi lintas generasi, kita sering menjumpai nada keluhan: “Anak sekarang susah diajak serius,” “mereka hidup di dunia maya,” “mereka rebahan, bukan pejuang.” Tapi siapa yang menentukan makna dari keseriusan, dari perjuangan, dari realitas? Tidakkah itu semua adalah bentuk-bentuk makna yang diproduksi oleh generasi sebelumnya, oleh struktur sosial yang menganggap kerja, gerak, dan produksi sebagai satu-satunya jalan menuju eksistensi yang sah?
Jika kita membacanya dari Iqbal, khudi bukanlah kecepatan, bukan pula kerja tanpa henti. Khudi adalah intensitas kesadaran diri. Ia bisa muncul dalam kontemplasi, dalam keraguan, bahkan dalam penolakan terhadap sistem nilai yang sudah mapan.
Generasi Z yang menolak bekerja dalam sistem yang dianggap eksploitatif, yang memilih jalan lambat, yang lebih peduli pada kesehatan mental daripada kecepatan promosi, mereka tidak sedang kehilangan eksistensi, mereka sedang menyusun ulang porosnya. Mereka sedang, seperti Iqbal tulis, menyingkirkan rintangan dalam jalan menuju kebebasan batin, dengan cara yang tak lazim tapi sah.
Sementara itu, dalam kacamata Sartre, Gen Z barangkali adalah representasi paling murni dari kondisi eksistensial manusia kontemporer. Manusia yang dilempar ke dunia tanpa kepastian, menghadapi absurdnya pilihan-pilihan identitas yang serba mungkin, namun tanpa pegangan absolut.
Gen Z tumbuh di tengah krisis iklim, ekonomi digital, dan realitas virtual. Mereka tidak punya Tuhan ekonomi seperti generasi sebelumnya. Mereka, dengan cara mereka sendiri, sedang menghadapi beban kebebasan yang brutal: memilih jadi apa, padahal tak ada peta yang pasti.
Sartre bilang manusia dikutuk untuk bebas. Dan barangkali, rebahan bukan tanda kelemahan, tapi cara eksistensial Gen Z untuk menghindari absurditas yang membunuh. Mungkin mereka tahu, seperti Sartre tahu, bahwa bergerak tanpa makna lebih menyakitkan daripada diam dengan kesadaran.
Maka pernyataan “mereka lemah” menjadi pertanyaan balik: lemah menurut siapa? Dalam dunia di mana kerja dianggap penyelamat, menolak bekerja bisa menjadi tindakan radikal. Dalam budaya di mana produktivitas menjadi Tuhan, pasif bisa jadi bentuk perlawanan.
Di sinilah kita mesti berhenti menilai Gen Z dengan parameter lama. Perlu diingat, pusat selalu bisa digeser, oposisi bisa dibalik, dan makna bisa ditunda. Barangkali, generasi ini tidak sedang krisis identitas, melainkan sedang menolak diberikan identitas oleh sistem yang gagal.
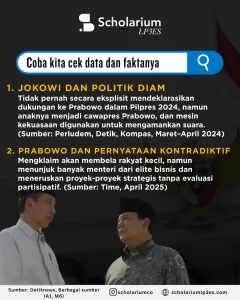
Kaum Rebahan Jangan Minder
Kita telah mengikuti jejak dua pemikir, Iqbal dan Sartre. Dua nama yang dalam sejarah filsafat eksistensial dianggap berdiri di kutub yang saling menolak, yang satu menenun makna dalam langit keilahian, yang satu membakar langit itu agar manusia berdiri tanpa atap.
Tapi kutub-kutub itu sering kali adalah produk dari ilusi logika biner. Karena baik khudi Iqbal maupun kebebasan Sartre, pada dasarnya sama-sama berbicara tentang satu hal: kegentingan menjadi manusia.
Dan ketika kita geser bingkai itu ke Generasi Z, yang dituduh lemah, pasif, hilang arah, kita justru menemukan potensi subversif. Mungkin mereka tidak sedang hilang, tapi menolak ditemukan. Mungkin mereka tidak sedang pasif, tapi sedang mengurai definisi lama tentang apa itu bergerak. Dan mungkin, mereka tidak lemah, melainkan sedang membongkar makna “kuat” itu sendiri.
Dalam dunia yang menyembah efisiensi, Gen Z hadir sebagai jeda. Dalam zaman yang menganggap produktivitas sebagai penyelamat, mereka menciptakan ruang kosong. Tapi ruang kosong bukanlah kekosongan. Ia adalah kemungkinan. Ia adalah tempat différance bekerja, bukan penundaan makna sebagai kekalahan, tapi sebagai strategi untuk menghindari perangkap finalitas.
Esai ini bukan simpulan, melainkan sebuah pembuka. Sebuah undangan untuk membongkar cara kita berpikir tentang generasi, tentang kebebasan, tentang manusia itu sendiri. Mungkin sudah waktunya kita tidak lagi bertanya, “Apakah Gen Z telah gagal menjadi manusia?”, melainkan: manusia seperti apa yang kita anggap sah?
Dan siapa yang berhak menentukan itu? Oleh karena itu, saya ingin berseru: “Wahai Kaum Rebahan Janganlah Minder”.