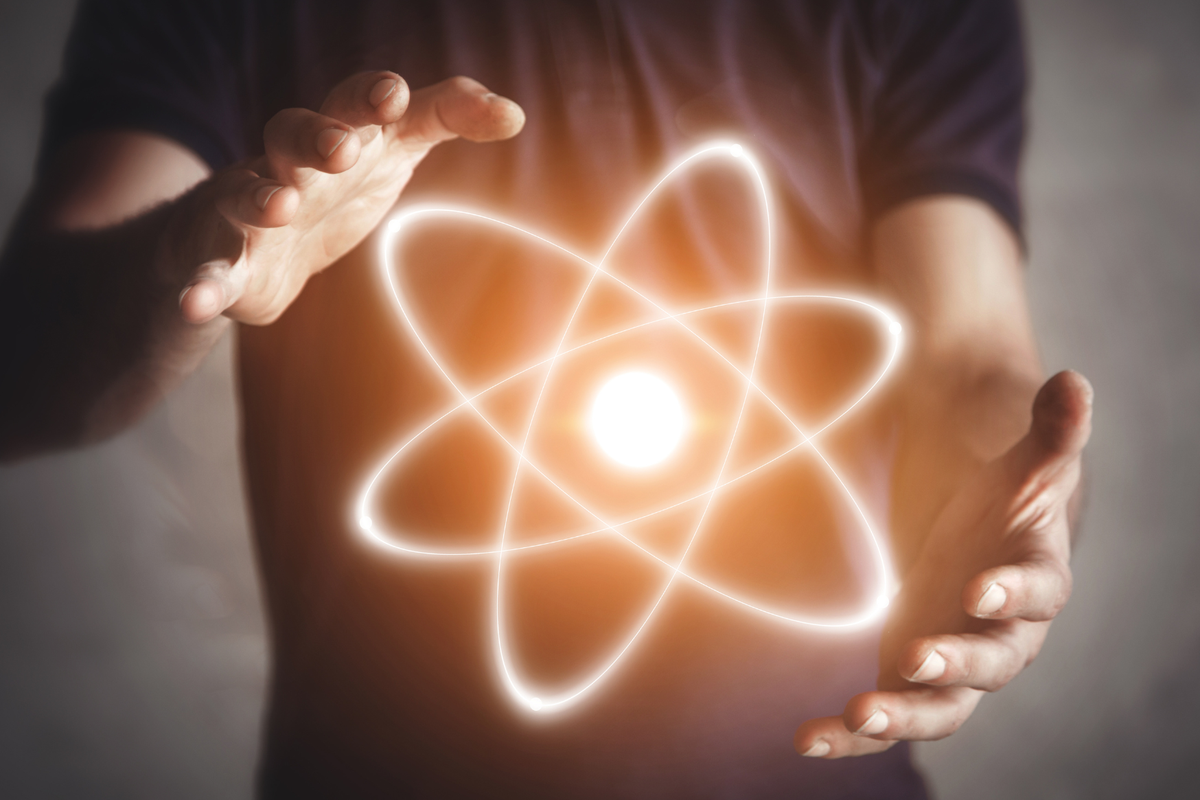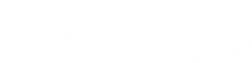Membaca Ulang Sumitro

Tatkala lembar-lembar pustaka mengabarkan nama Sumitro, tiadalah ia semata sesosok ekonom yang memahat angka di buku-buku tua. Ia ialah saksi zaman, penggubah kalkulasi yang berdenyut di antara impian bangsa dan cengkraman realitas. Membaca Sumitro hari ini, bukanlah sekadar mengorek abu nostalgia, melainkan menimba hikmat ihwal bagaimana negeri ini pernah menggubah siasat, menanggung getir, dan menghayati keraguan dengan kepala tegak.
Sumitro Djojohadikusumo bukan semata nama besar yang tercatat dalam riwayat perekonomian Indonesia, melainkan gugus pemikiran yang terpatri di lembar-lembar pustaka; sebagian tinggal serpih tua yang nyaris lapuk, sebagian bangkit dalam wujud baru, terus dijelajahi dan ditafsir ulang dari masa ke masa.
Dari Kredit Rakyat di Masa Depresi (1977), Science, Resources and Development (1980), Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan (1982), Indonesia dalam Perkembangan Dunia: Kini dan Masa Datang (1986), hingga Perkembangan Pemikiran Ekonomi (1994)—semuanya diterbitkan oleh LP3ES—terhampar bentang pemikiran Sumitro yang jauh melampaui kalkulasi angka dan kurva. Ia menulis dengan nalar seorang ekonom, namun merenung dengan jiwa seorang negarawan yang memandang ekonomi sebagai panggung bagi harkat dan martabat bangsa.
Tak hanya karya-karyanya sendiri, pemikiran Sumitro pun telah menjadi bahan telaah dan tafsir ulang para pemikir lain, terutama Dawam Rahardjo, yang menelusuri sekaligus mengkritisi corak pragmatisme dalam nasionalisme ekonomi Indonesia melalui dua kitab penting: Pragmatisme dan Utopia: Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia (1992) dan Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme (2017). Dalam kedua pustaka ini, Sumitro hadir bukan semata sebagai ekonom kebijakan, melainkan sebagai figur ideologis yang posisinya senantiasa bergerak di antara visi, kompromi, dan siasat.
Bahkan setelah puluhan tahun berlalu, kitab-kitab ini tetap bergema; bukan lantaran semata hendak memaksakan konteks silam ke pangkuan masa kini, melainkan sebab di dalamnya terhimpun pelbagai cara memandang, mengurai, dan merancang ihwal masa depan yang belum juga usai.
Penafsiran ulang atas Sumitro kian memperoleh gema tatkala kita menyadari bahwa putra kandungnya, Prabowo Subianto, kini menyandang amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Nama Sumitro pun muncul kembali, bukan semata sebagai serpih nostalgia sejarah, melainkan sebagai kerangka pikir yang hendak dirujuk—atau barangkali diselewengkan—untuk menakar arah kebijakan pemerintahan yang baru ini. Namun apakah sesungguhnya makna “membaca Sumitro” di ambang zaman kini?
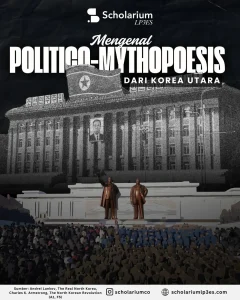
Ekonomi dalam Tahun-Tahun Genting
Membaca kembali Sumitro pada hari ini menuntut kita menuntaskan pemahaman atas konteks sejarah yang melatari segenap jaring pikirannya, suatu latar yang dikupas dengan tajam dalam Recollections: The Indonesian Economy, 1950s–1990s (2003). Dalam wawancara yang termaktub di dalamnya, Sumitro memaparkan dengan jernih pelbagai tantangan ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan: struktur dagang yang dikuasai modal asing, keterbatasan fiskal, lemahnya institusi negara, serta ketiadaan kelas pengusaha nasional.
Tatkala menjabat Menteri Perdagangan dan Industri (1950–1951), Sumitro merumuskan Program Benteng, suatu kebijakan afirmatif guna memberi lisensi impor kepada pengusaha bumiputra. Program ini berikhtiar meretas dominasi kolonial yang masih melekat dalam urat dagang republik muda. Meski ia menyadari bahwa dari sepuluh pengusaha yang memperoleh akses, barangkali hanya tiga yang benar-benar bertunas, ia tetap mendorongnya sebagai langkah strategis jangka panjang, alih-alih semata upaya perbaikan sesaat.
Namun Sumitro tiadalah semata perumus kebijakan. Ia pun pengamat nan tajam atas gelanggang pertarungan antara gagasan dan kenyataan. Sumitro bergulat di antara dua kutub besar: semangat nasionalisme pascakolonial yang mendesak pengambilalihan harta ekonomi asing, dan keperluan praktis untuk menegakkan ketenteraman ekonomi negeri yang baru terlahir.
Dalam suasana defisit anggaran sebesar Rp 1,7 juta pada 1950, yang kemudian tertutup oleh surplus tak terduga lantaran Korea boom pada tahun berikutnya, Sumitro memperlihatkan bahwa ketenteraman fiskal tidak selalu menuntut ideologisasi, melainkan kebijakan yang lentur dan peka terhadap gelombang ekonomi global. Namun surplus itu tak berusia panjang. Tatkala ekspor merosot dan konsumsi barang mewah menjulang, Indonesia kembali terjerembap dalam defisit. Sumitro pun mesti berhadapan dengan inflasi yang menggigit, kelangkaan devisa, serta desakan nasionalisasi yang kian menguat di parlemen dan jalanan.
Salah satu langkah paling ambisius yang dirumuskannya ialah Rencana Urgensi Ekonomi (1951), yang menempatkan industrialisasi sebagai poros pembangunan nasional. Dalam pandangan Sumitro, Indonesia mesti memiliki landasan industri sendiri agar mampu melepaskan diri dari belenggu ketergantungan pada bahan mentah.
Namun rencana ini kerap terseok oleh rapuhnya kapasitas teknis, birokrasi yang berbelit, dan kekurangan tenaga ahli. Ia pun tiada menutup mata atas kenyataan itu; Sumitro sendiri mencatat bahwa “kegagalan organisasi dan buruknya manajemen” menjelma hambatan yang paling getir. Dalam teropong semacam inilah kita menyaksikan sosok Sumitro sebagai seorang economics-minded administrator—meminjam istilah Benjamin Higgins—yang lebih memilih ketenteraman fiskal dan rasionalitas ketimbang retorika populis yang kian lantang di bawah kepemimpinan Sukarno.
Sumitro pada akhirnya bukan semata produk dari zamannya, melainkan pula saksi atas bagaimana ekonomi pascakolonial dirajut oleh tarik-menarik antara nasionalisme, kebutuhan pembangunan, dan kelangkaan kapasitas.
Maka tatkala kita bertanya mengapa Sumitro patut dibaca kembali hari ini, jawabannya barangkali justru terletak pada kejujurannya sebagai pemikir: ia tiada menjanjikan utopia, melainkan menawarkan kalkulasi. Dan dari kalkulasi itulah, kita dapat menakar apakah warisan buah pikirnya masih memiliki daya tawar dalam menghadapi problem struktural Indonesia yang belum jua usai.
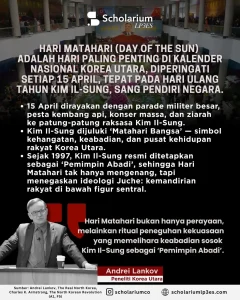
Teks yang Terus Bergerak
Untuk menyingkap Sumitro di masa kini, tiadalah cukup sekadar membuka kembali kitab-kitabnya atau mengutip kebijakan yang pernah ia rancang. Yang diperlukan ialah pembacaan yang lebih jernih dan menyeluruh, dan di sinilah pendekatan hermeneutik membuka suatu jalan yang bernas.
Hermeneutik, sebagaimana tumbuh dari pemikiran Schleiermacher hingga Gadamer dan Paul Ricoeur, memungkinkan kita menempatkan teks sebagai ruang makna yang tiada pernah tunggal. Membaca Sumitro, dalam pengertian ini, berarti menafsir teks-teks ekonominya sebagai lanskap yang sarat ragam pertalian: pertalian antara teks dan pengarangnya (aspek autorial), antara teks dan konteks historis ketika ia menulis (aspek kontekstual), serta antara teks dan kita sebagai pembaca yang hidup dalam kurun yang lain (aspek resepsionis).
Tatkala Sumitro menulis ihwal “pembangunan pengusaha nasional”, ia tiada sekadar mengulang jargon politik, melainkan tengah menggugat struktur ekonomi kolonial melalui jalur perencanaan yang disadarinya dapat dinegosiasikan setahap demi setahap, meski ia maklum benar jalan itu sarat kompromi dan kegagalan yang tak terelakkan.
Namun justru lantaran itu, teks-teks Sumitro tak dapat dibaca semata sebagai formula, melainkan sebagai negosiasi yang berlapis. Kita tiada cukup menafsirkannya dalam batas hubungan kebahasaan atau teknokratiknya saja (aspek tekstual), melainkan pula dalam ketegangannya dengan konteks politik zamannya yang anti-Barat dan diliputi euforia revolusioner.
Sumitro tiada menulis untuk merapal puja-puji kemajuan, melainkan untuk mencari celah di tengah belantara problem bangsa yang baru berjejak: antara nasionalisasi dan efisiensi, antara ideologi dan anggaran, antara mimpi dan neraca. Maka membaca Sumitro hari ini bukanlah perihal menggali preskripsi atau semacam “resep obat” bagi kebijakan ekonomi masa kini.
Apalagi jika sekadar dipakai untuk membenarkan ataupun mencela arah politik putranya; lebih penting memahami bahwa warisan sejati Sumitro adalah sikap epistemik terhadap perkara: bahwa ekonomi merupakan ladang perdebatan rasional, bukan sekadar alat legitimasi.
Dengan demikian, pembacaan atas Sumitro pada hari ini mesti melampaui pendekatan yang linear dan ahistoris. Ia menuntut kesadaran bahwa makna tiada selalu terhampar di permukaan kalimat, melainkan lahir dari pertemuan antara teks, sejarah, dan imajinasi pembaca di masa kini. Maka, bila Sumitro hanya dibaca sebagai “bahan bakar ideologis” bagi Prabowo, kita justru berisiko mengingkari keruwetan dan kelimpahan makna yang terkandung dalam warisan buah pikirnya.
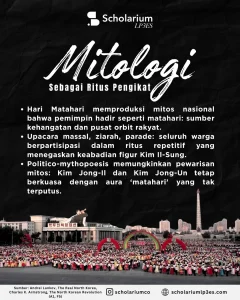
Tafsir Dawam dan Kritik Hari Ini
Dawam Rahardjo, dalam dua karyanya yang penting—Pragmatisme dan Utopia: Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia (1992) serta Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme (2017)—telah melakukan apa yang dapat disebut sebagai pembacaan reflektif atas Sumitro. Ia tiada hanya mencatat biografi intelektual Sumitro, melainkan menelusuri corak berpikir yang sekaligus mengayakan dan membatasi langkah-langkah kebijakan sang tokoh.
Bagi Dawam, Sumitro menjelma personifikasi nasionalisme ekonomi yang khas Indonesia: tiada revolusioner, tetapi berikhtiar merebut penguasaan atas alat-alat produksi secara berangsur; tiada menolak kapitalisme, namun berupaya memadukannya dengan cita-cita kemandirian nasional.
Yang istimewa dari tafsir Dawam ialah bahwa ia tiada memandang pragmatisme sebagai cela atau kelemahan, melainkan sebagai realisme politik-ekonomi seorang pemikir yang mafhum kapan mesti merancang, dan kapan harus menyingkir setapak demi menempuh jalan lain. Itulah sebabnya, meskipun Sumitro kerap dikritik lantaran terlalu “ekonom teknokrat” dan kurang politis, justru dalam pembacaan Dawam-lah Sumitro memperoleh kedalaman: ia tak tunduk sepenuhnya pada pasar, namun juga tak hendak menyerahkan seluruh ihwal ekonomi ke pangkuan negara.
Namun berlainan dari pembacaan Dawam yang berwatak tafsir reflektif, banyak pembacaan masa kini justru cenderung menjadikan Sumitro sebagai “figur pelindung ideologis”, semacam nama besar yang lekas dipinjam guna memberi legitimasi pada arah kebijakan Prabowo Subianto.
Di sinilah terletak kerentanan dalam membaca seorang tokoh intelektual, tatkala bayang-bayang kekuasaan menggiring warisan pemikiran menjadi sekadar hiasan retoris belaka. Sumitro dihadirkan kembali bukan sebagai pemikir yang patut dikritisi dan diperdebatkan, melainkan sebagai ayah biologis yang seolah lebur dengan agenda politik sang anak.
Padahal, sebagaimana diajarkan oleh hermeneutika, teks tiada patut dipaksa tunduk pada kehendak pembaca; justru pembaca-lah yang mesti menegosiasikan dirinya dengan jagat makna yang ditawarkan oleh teks. Maka, bila Sumitro dibaca semata untuk mengukuhkan slogan “ekonomi nasionalis-kerakyatan”, tanpa menyentuh kompleksitas strategi yang pernah ia rancang, itu bukan lagi pembacaan, melainkan penyempitan makna.

Membaca Indonesia Melalui Sumitro
Karena itu, membaca kembali kitab-kitab Sumitro tiada semata perihal mengulik masa silam demi nostalgia, ataupun sekadar mencari pembenaran historis bagi pemimpin hari ini. Ia adalah ikhtiar untuk menyingkap bagaimana gagasan ekonomi nasional pernah dirumuskan, dinegosiasikan, dan diuji di tengah realitas Indonesia yang sarat batas dan gejolak.
Dari Kredit Rakyat di Masa Depresi (1977) hingga Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan (1982), dari Science, Resources and Development (1980) hingga Perkembangan Pemikiran Ekonomi (1994), Sumitro mewariskan lebih dari sekadar teori atau kebijakan; ia meninggalkan cara berpikir tentang negara, pembangunan, dan rakyat yang tak berhenti pada dogma semata.
Membaca buku-buku Sumitro tetaplah penting, bukan semata lantaran konteksnya yang masih bergema, melainkan karena kita perlu belajar dari caranya merumuskan persoalan dan menimbang pelbagai pilihan, bukan hanya dari ihwal hasil akhirnya. Di dalam dunia yang gemar mengidolakan simpulan cepat dan slogan ringkas, Sumitro mengajak kita berjalan perlahan, dengan keraguan yang sehat dan akal yang bening.
Di sinilah kita mesti berjaga-jaga: Sumitro tiadalah semata jembatan untuk menafsir Prabowo, dan tak seharusnya demikian. Pemikiran Sumitro adalah jendela untuk menyingkap Indonesia dalam segenap sejarah, ketegangan, dan pelbagai kemungkinan yang dikandungnya.
Menggiring Sumitro menjadi sekadar pisau untuk menilai anaknya bukan hanya reduksi, melainkan pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang pernah ia junjung. Sumitro tiada menulis demi dinasti, ia menulis demi negeri.
Maka, membaca Sumitro pada hari ini adalah ikhtiar untuk menyingkap Indonesia dengan lebih jujur, lebih lapang, dan lebih berani, terlebih tatkala masa depan kembali digenggam oleh mereka yang mengaku membawa nama besarnya.