Dunia Maya Raja Ampat

Di negeri telur yang membatu dan laut yang disebut ibu, mitos bukan cerita masa lalu, melainkan cermin yang menegur masa kini. Tapi ketika batu raja dibungkam oleh suara bor, dan tanah disulap jadi izin tambang, kita dipaksa bertanya: siapa yang sebenarnya buta?
Menjadi “Maya” bukan sekadar soal garis keturunan atau wilayah geografis, ia adalah semesta makna yang terjalin antara darah, laut, dan mitos. Dalam lanskap sosial Raja Ampat, etnik Maya merupakan representasi dari suatu bentuk masyarakat kepulauan yang hidup di antara darat dan laut, dalam arti harfiah dan simbolis. Mereka tersebar di Pulau Waigeo, Salawati, dan Teluk Mayalibit, menempati hanya sebagian kecil dari ribuan pulau Raja Ampat, namun mengisi ruang budaya dengan makna yang dalam.
Dalam narasi masyarakat Maya, laut bukan sekadar ruang eksploitasi sumber daya, tetapi ibu yang melahirkan kehidupan, sedangkan tanah adalah bapak, pemberi identitas dan keteguhan. Ini adalah oposisi simbolik yang menunjukkan bukan hanya cara hidup, melainkan juga cara berpikir.
Namun menjadi Maya juga berarti menjadi bagian dari sejarah yang lebih besar, jaringan kuasa dan darah yang merentang ke arah barat, ke Kesultanan Tidore. Dalam Sonyine Malige -museum Memorial Kesultanan Tidore- disebutkan bahwa masyarakat Raja Ampat merupakan peranakan Tidore, dan melalui akulturasi dengan Papua Timur dan Maluku, terbentuklah entitas yang kini dikenal sebagai “pribumi Maya”. Melalui perkawinan antar-etnis dan penyebaran kekuasaan kultural, Maya menjadi medan tafsir dari “simbol realitas sosial” yang dijalin lewat cerita, ritual, dan struktur sosial.

Dunia Maya dan Awal Telur
Dalam mitologi etnik Maya, dunia tidak sekadar dimulai dari suatu letupan biologis, melainkan dari sebuah telur, sebuah simbol yang begitu sarat makna. Dalam Mitos Kerajaan Raja Ampat, muncul narasi tentang tujuh telur yang menjadi cikal bakal leluhur masyarakat Maya. Salah satu dari telur itu tak menetas, tetapi membatu, dan kemudian diperlakukan layaknya seorang raja, dimandikan, dibungkus kain putih, dijaga oleh dua batu pengawal, bahkan diberi kelambu dan payung kerajaan.
Di sinilah simbol bekerja secara maksimal. Raja bukan sekadar figur administratif, melainkan lambang dari kosmos itu sendiri, dan dalam konteks Maya, kekuasaan justru dilahirkan dari yang transenden, bukan dari yang manusiawi. Batu itu menjadi locus sakral yang menghubungkan manusia Maya dengan dunia atas –makrokosmos– yang penuh kekuatan roh dan leluhur.
Apa yang dalam masyarakat Barat disebut sebagai “institusi politik,” dalam konteks Maya menjadi sesuatu yang nyaris religius. Sosok raja tidak diangkat melalui kontrak sosial, tetapi melalui keajaiban, lahir dari telur, hadir dalam mimpi, atau diberi tanda oleh alam.
Gelar raja yang diberikan pada keturunan langsung raja Salawati misalnya, bukan hanya simbol penghargaan atas jasa, tetapi juga perwujudan silsilah sakral yang merujuk ke Kesultanan Tidore, ke Biak, ke Seram, ke jalinan sejarah yang membentuk tubuh budaya Maya. Dengan demikian, kekuasaan bukan hanya diwariskan, tetapi dimaknai, dipelihara, dan direproduksi dalam ritual seperti Kali Raja, tempat di mana dunia gaib dan dunia kasat mata bertemu dalam upacara simbolik.
Dalam dunia Maya, oposisi bukanlah pertentangan, melainkan tatanan. Ia adalah bentuk dari cara mereka memberi makna pada hidup, yang mengatur siapa melakukan apa, dan di mana. Darat dan laut bukan sekadar bentang geografis, tetapi lambang dari dua prinsip utama kehidupan: laki-laki dan perempuan, keras dan lembut, tetap dan berubah.
Para lelaki Maya turun ke laut, menyelam, mencari ikan, menantang ombak. Sementara perempuan tinggal di darat, menyulam, menanak sagu, menjaga api tetap menyala. Tapi dalam pembagian ini tidak ada subordinasi. Yang tertanam adalah harmoni, keseimbangan antara dua dunia yang sama pentingnya bagi keberlangsungan hidup.
Makna oposisi ini tidak hanya hidup dalam praktik sehari-hari, tetapi juga dalam mitos dan simbol: kura-kura yang dapat hidup di dua alam menjadi metafora dari manusia Maya itu sendiri, mereka yang luwes, cair, mampu hidup dalam ketegangan antara tanah dan laut. Bahkan makanan mereka pun mencerminkan oposisi ini: sagu dari darat, suntung dari laut, ganemo dari kebun, taripang dari selat-selat.
Tindakan Masyarakat sehari-hari ini adalah “teks-teks budaya”, ritus yang diulang dan mengandung makna yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ketika seorang laki-laki mengangkat panikam untuk menikam ikan, atau seorang perempuan mengiris daun gedi di dapur, mereka tidak hanya bekerja: mereka sedang mereproduksi sistem kosmologis, memperkuat posisi mereka dalam jaringan simbol yang menyusun masyarakat.

Kepercayaan Mon dan Sakralitas Bayang
Di tepi Kali Raja, selembar kain putih membalut sebongkah batu. Di bawah payung kerajaan dan kelambu halus, ia dijaga dua batu lain bernama Manmoron dan Manmeten. Tapi ini bukan batu biasa. Ini adalah Raja. Leluhur. Cikal bakal. Dalam sistem kepercayaan Mon –agama leluhur Maya sebelum datangnya Islam dan Kristen– benda-benda alam adalah tempat bersemayamnya kekuatan gaib yang berasal dari dunia atas, atau makrokosmos.
Para leluhur tidak mati; mereka berubah bentuk, menitis dalam batu, telur, bahkan dalam mimpi. Ritual “memandikan dan mengganti pakaian raja” bukanlah upacara folkloris semata, melainkan tindakan sakral untuk menjaga keseimbangan kosmis antara dunia gaib dan dunia nyata.
Praktik semacam ini sebagai bentuk “drama sosial” yang tidak hanya memetakan makna, tapi juga meneguhkan sistem moral dan tatanan dunia. Upacara Kali Raja adalah panggung tempat manusia Maya memainkan keyakinan mereka terhadap hubungan vertikal antara dunia bawah dan atas.
Dunia bawah adalah tanah, sungai, tubuh manusia, penari, alat musik, dan makanan. Dunia atas adalah roh, mimpi, dan batu raja yang bisu namun sakral. Dalam pandangan kosmologi Maya, manusia adalah perantara yang menjembatani dua dunia ini, tugas yang berat dan sakral, yang diwariskan lintas generasi.
Yang menarik, keyakinan ini tidak berjalan sendiri. Ia berkelindan dengan narasi asal-usul dari telur, simbol keturunan ilahi, dan juga dengan jejak Kesultanan Tidore yang memberi “izin” simbolik terhadap gelar raja. Maka dalam satu ritual, termuat lapisan religius, historis, dan politik, memperlihatkan jaringan simbol yang kaya dan saling mengikat.
Jika mitos adalah sistem pengetahuan, maka etnik Maya telah lama hidup dalam universitas yang dibangun oleh laut, batu, dan kata-kata. Dalam Handbook of Native American Mythology (2004), para sarjana budaya E. Dawn Bastian dan Judy K. Mitchell menyatakan bahwa mitos memiliki dua fungsi utama: fungsi primer, untuk menjelaskan realitas alam dan membenarkan sistem sosial serta adat tradisional; dan fungsi sekunder, sebagai wahana pembelajaran, penyembuhan, dan sumber inspirasi bagi masyarakat tradisional.
Dalam konteks Raja Ampat, Mitos Kerajaan bukan hanya menjelaskan asal-usul manusia Maya dari telur-telur gaib, tetapi juga memvalidasi keberadaan mereka hari ini, sebagai pewaris sah bukan hanya pulau-pulau yang indah, tetapi juga sejarah yang dalam. Mitos menjadi medium yang membuat identitas mereka tetap hidup dalam dunia yang cepat berubah.
Dalam era kontemporer, saat Raja Ampat menjelma menjadi ikon pariwisata global, mitos itu tidak luntur, ia justru menemukan peran baru. Ia menjadi narasi kultural yang menahan laju komodifikasi pariwisata agar tidak menjadikan pulau-pulau ini sekadar objek eksotisme.
Mitos menjaga harkat ruang sakral, memberi batas antara yang boleh dilihat dan yang hanya boleh dipercayai. Di sinilah fungsi sekunder mitos bekerja: memberi pelajaran kepada generasi muda tentang pentingnya keseimbangan, tentang kerendahan hati di hadapan alam, dan tentang perlunya menyayangi dunia seperti menyayangi leluhur.
Simbol-simbol itu, dari batu raja hingga telur burung maleo, tidak berhenti hidup dalam cerita lama, mereka menyelinap ke dalam kesadaran ekowisata, menjadi bagian dari narasi yang dijual, dilestarikan, dan dibanggakan. Maka, antara snorkel dan selendang bidadari, antara penyelam asing dan ritual Kali Raja, terdapat benang yang tak kasat mata namun kuat: benang yang ditenun oleh mitos dan ditarik dari masa lalu untuk menjaga masa depan.
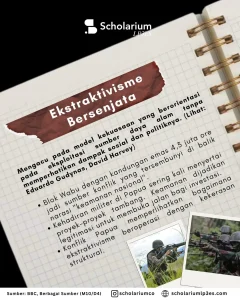
Kala “Energi” Jahat Datang
Datanglah kekacauan dengan bor dan ekskavator, merusak narasi sakral yang telah lama dijaga oleh mitos. Pada bulan Juni 2025, protes meletus ketika Greenpeace dan aktivis adat mengungkap praktik penambangan nikel di pulau-pulau kecil seperti Gag, Kawe, dan Manuran –termasuk areal konservasi dan cagar laut– yang telah membabat lebih dari 500 hektare hutan serta mencemari sungai dan terumbu karang melalui sedimentasi. Demonstrasi bahkan mencapai bandara Sorong, di mana massa meneriakkan “Bahlil Penipu” kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dianggap menghindari dialog dengan rakyat adat selama kunjungannya ke lokasi tambangr.
Sementara pemerintah melalui kementerian ESDM dan KLH menyebut dampak pencemaran “relatif minor” dan mengklaim lahan telah direklamasi, aktivis dan sejumlah anggota DPR mempertanyakan izin yang dianggap melanggar undang-undang serta terindikasi ada unsur KKN.
Kekacauan ini membentuk pola simbolik, bukan sekadar konflik politik, tetapi manifestasi pergeseran nilai. Tambang bertemu dengan mitos, dan kerusakan dunia nyata menjadi rapuhnya keseimbangan kosmos yang selama ini dipelihara melalui ritual seperti Kali Raja.
Di sinilah ironi muncul, kekayaan alam yang dielu-elukan sebagai simbol kemajuan (nikel untuk baterai hijau) justru mengancam landasan kosmologis masyarakat Maya, dunia atas dan bawah kini terguncang. Ketika mitos tak mampu menjaga batasan, maka ritual menjadi pedang bermata dua, menjaga sekaligus rusak. Tambang bukan lagi narasi logis tentang keuntungan atau kerugian, tetapi bab baru dalam teks budaya Raja Ampat yang penuh konflik, ketegangan, dan perlawanan.
Apa arti tambang bagi sebuah masyarakat yang mendefinisikan laut sebagai “ibu” dan tanah sebagai “bapak”? Ketika darat dikeruk dan laut dicemari, itu bukan sekadar perusakan lingkungan, melainkan pengingkaran terhadap asas ontologis kehidupan etnik Maya.
Dalam kosmologi mereka, seperti yang termuat dalam mitos dan ritus, hubungan antara manusia dan alam adalah relasi spiritual. Alam bukan objek, tetapi subjek yang memiliki kehendak, marah bila dilukai, dan memberi bila dihormati. Dalam kerangka ini, kehadiran tambang nikel bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi invasi epistemologis yang membawa logika kapital ke dalam ruang yang selama ini diatur oleh logika kosmik.
Secara filosofis, tambang mewakili cara pandang dunia modern yang memisahkan roh dari benda, nilai dari material, dan manusia dari alam. Sementara dalam worldview Maya –dan masyarakat adat secara umum– realitas bersifat holistik dan sakral.
Mitos Raja Ampat adalah manifestasi dari apa yang filsuf Immanuel Kant sebut sebagai noumena, dunia batiniah yang tak bisa disentuh akal empiris. Maka ketika penggusuran dilakukan atas nama pembangunan, masyarakat tidak hanya kehilangan ruang hidup, tetapi juga kehilangan dunia mereka, dalam arti yang paling harfiah dan paling metafisis.
Tambang juga menimbulkan fragmentasi sosial: konflik antara elite yang merestui izin dan warga adat yang menolak, antara negara yang mengklaim kepentingan nasional dan komunitas yang memperjuangkan hak wilayah adat.

Raja Ampat sebagai Teks
Raja Ampat hari ini bukan sekadar gugusan surga yang diburu lensa para pelancong dunia. Ia adalah teks yang sedang ditulis ulang oleh sejarah, oleh mitos, oleh konflik, dan oleh kapital.
Dari batu raja yang dibungkus kain putih hingga laut yang disulap menjadi zona industri nikel, semuanya adalah simbol yang saling bertaut. Jika kita membaca Raja Ampat hanya sebagai destinasi, kita kehilangan setengah dari maknanya. Sebab bagi etnik Maya, tempat ini bukan sekadar ruang geografis, tetapi ruang kosmologis, ruang di mana tubuh mereka, leluhur mereka, dan Tuhan mereka bersatu dalam ritus yang sakral.
Lebih bijak jika kita untuk tidak sekadar mengamati budaya, tetapi mengartikulasikannya. Dalam konteks itu, konflik tambang adalah lebih dari sekadar polemik sumber daya, ia adalah pertarungan antara dua teks: satu ditulis dengan bahasa batu dan telur, yang satu lagi dengan bahasa logam dan saham. Di tengahnya, masyarakat Maya berdiri seperti kura-kura dalam mitos mereka: bertahan di dua dunia yang terus menarik mereka ke arah yang berlawanan.
Raja Ampat, dalam makna terdalamnya, bukan hanya milik peta, tetapi milik makna. Jika kita ingin menyelamatkannya, kita harus terlebih dahulu membacanya. Tidak cukup dengan menyelam ke dalam lautnya, kita harus menyelam ke dalam ceritanya.
Di situlah tugas kita hari ini, menjaga agar teks ini tidak rusak, agar batu raja tetap dilindungi, dan agar mitos tetap hidup di tengah gempuran dunia yang sering kali lupa bagaimana cara mendengarkan.






