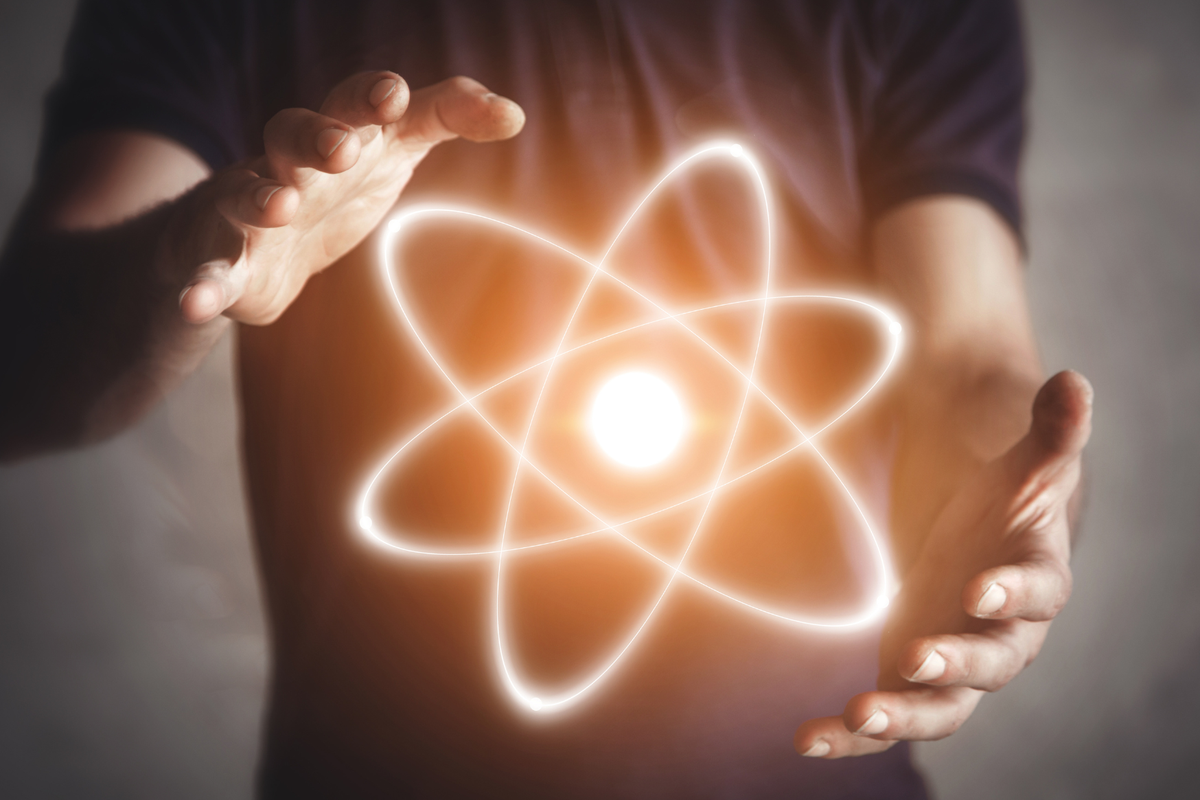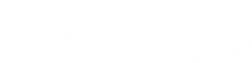Gaji Hakim Naik, Korupsi Naik?

Apakah gaji akan selalu berbanding lurus dengan integritas? Pertanyaan ini ditujukan kepada para Hakim di Indonesia, yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik karena persoalan korupsi melibatkan pada pengadil ini. Tulisan ini akan mengulik bagaimana langkah negara untuk menaikkan gaji hakim bukanlah solusi “tunggal” yang efektif untuk meningkatkan integritas hukum dan peradilan.
Upaya meningkatkan integritas di kalangan hakim masih menjadi pekerjaan rumah yang belum kunjung tuntas. Hal ini tercermin dari masih adanya kasus-kasus keterlibatan hakim dalam pusaran korupsi.
Kali ini, Presiden Prabowo berupaya memutus mata rantai tersebut dengan menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Tujuannya jelas: agar hakim tidak mudah disogok dan tidak bisa dibeli. Jika dihitung, gaji hakim golongan IIIA yang sebelumnya berkisar antara Rp2.785.700 hingga Rp4.575.200 kini naik menjadi Rp7.779.960 hingga Rp12.810.560. Sementara itu, gaji hakim golongan IVE naik dari Rp3.880.400–Rp6.373.200 menjadi Rp10.865.120–Rp17.844.960.
Saya mengapresiasi langkah ini sebagai bentuk nyata dari upaya menyejahterakan aparat peradilan. Namun demikian, pertanyaan penting tetap mengemuka: apakah peningkatan gaji semata cukup untuk membangun integritas? Ini justru yang perlu dikaji secara lebih mendalam.
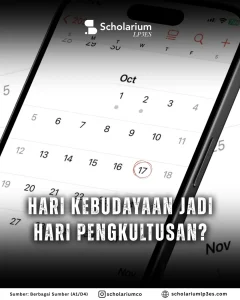
Gaji Bukan Satu-Satunya
Bagi saya, memandang integritas semata-mata dari sisi gaji adalah penyederhanaan yang keliru, bahkan berbahaya. Pendekatan semacam ini justru berpotensi membuka celah bagi bentuk korupsi atau suap yang lebih besar: semacam persaingan uang dalam menentukan moral.
Filsuf Michael Sandel, dalam kerangka filsafat moral dan ekonomi politik, pernah mengingatkan bahwa “tidak semua nilai bisa atau seharusnya diukur dengan uang.” Jika kejujuran dan keadilan diperlakukan sebagai komoditas, maka nilai-nilai itu akan tunduk pada logika pasar.
Sebagai ilustrasi, ketika hakim diberi gaji besar, ada risiko munculnya logika transaksional: “Jika negara bisa membayar saya untuk tidak korup, maka pihak lain—seperti pemilik modal besar—juga bisa membayar lebih tinggi untuk membeli kompromi saya.” Dalam situasi ini, integritas tidak lagi berpijak pada nilai etik, melainkan pada nilai tukar. Dan pasar –terutama pasar oligarki—selalu punya potensi menawarkan harga yang lebih tinggi dari negara.
Maka, menambatkan integritas hanya pada gaji adalah ilusi. Integritas harus bertumpu pada pendidikan moral, pengawasan publik, serta ekosistem hukum yang menumbuhkan keteladanan dan akuntabilitas, bukan sekadar nominal di slip gaji.
Dengan demikian, kita menyadari bahwa integritas bukan semata soal gaji, melainkan soal yang jauh lebih dalam dan kompleks. Menyambung hal itu, penelitian Eman Suparman menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan hakim, yang telah diinisiasi Komisi Yudisial bersama Pemerintah dan Parlemen melalui peningkatan tunjangan, ternyata belum signifikan dalam mengikis perilaku korup oknum hakim yang bermental serakah.
Logika bahwa kesejahteraan otomatis melahirkan integritas justru bisa menjadi jebakan yang merugikan negara. Uang negara dikeluarkan dalam jumlah besar untuk menggaji hakim, tapi keadilan masih saja sulit ditemukan.
Di zaman ketika uang disejajarkan dengan “Tuhan” dalam arti, siapa yang punya uang bisa melakukan apa saja, jangan sampai justru mata para hakim diarahkan ke tumpukan uang itu. Sebaliknya, arahkanlah dua matanya: mata penglihatan dan mata hati, pada satu tujuan, yaitu muara keadilan.
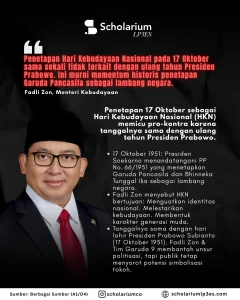
Reformasi Seleksi dan Etika
Sampai hari ini, banyak hakim masih menempatkan diri semata-mata sebagai corong undang-undang, sebuah posisi yang dianggap paling aman. Namun dalam kerangka hukum progresif, pola pikir semacam ini justru menunjukkan ketidakberanian untuk melakukan terobosan hukum, bahkan ketika menyangkut isu-isu kemanusiaan atau pemerintahan yang bersih. Sebab memang, dalam praktiknya, keadilan kerap saling bertarung dengan legalitas.
Kasus Masyarakat Adat Suku Anak Dalam di Jambi adalah contoh nyata. Mereka masih mencari keadilan setelah tanah leluhur mereka—yang telah dihuni dan menjadi sumber kehidupan selama ratusan tahun—diberikan pemerintah kepada perusahaan sawit dan tambang. Hak-hak mereka sebagai warga negara, dan sebagai manusia, diabaikan dalam logika hukum yang terlalu formal dan berpihak pada kekuatan modal. Ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak asasi manusia masih menghadapi banyak tantangan, baik dari aspek hukum, politik, sosial, maupun budaya.
Maka dari itu, menuju keadilan tidak bisa dimulai hanya dari soal gaji. Jika integritas semata ditentukan oleh besar kecilnya penghasilan, maka siapa pun bisa direkrut menjadi hakim, bahkan pencuri sekalipun. Tidak perlu lagi ada syarat administrasi, akademik, atau seleksi karakter. Padahal, integritas adalah soal mindset dan moral core—nilai-nilai moral inti—yang terbentuk dalam kurun waktu panjang melalui pendidikan, pengalaman, dan pembiasaan hidup jujur.
Dalam tulisannya, Iwan Satriawan meneliti Implikasi Mekanisme Seleksi terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia. Temuannya menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara mekanisme seleksi—apakah terbuka atau tertutup—dengan kualitas hakim konstitusi yang dihasilkan. Singkatnya, proses seleksi yang baik dan transparan cenderung melahirkan hakim yang berintegritas dan mandiri. Sebaliknya, seleksi yang tertutup dan tidak akuntabel justru memunculkan hakim yang rapuh secara etika dan mudah diintervensi.
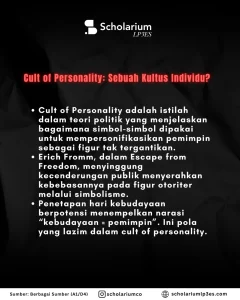
Integritas Bukan Komoditas
Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa gaji hanyalah satu elemen kecil dari sistem tata kelola peradilan. Pilar integritas sejati justru bertumpu pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta tegaknya rule of law. Jika pemerintah sungguh ingin menciptakan hakim yang berintegritas, maka strategi utamanya bukan semata menaikkan gaji, melainkan memperkuat pemahaman etika dan moral core dalam tubuh peradilan. Ini harus disertai dengan sistem seleksi yang ketat namun terbuka, serta pengawasan yang melembaga.
Mereduksi integritas menjadi persoalan ekonomi adalah kekeliruan besar. Jika kenaikan gaji dimaksudkan untuk “membeli” integritas, maka logika yang sama dapat digunakan oleh kekuatan modal: suap dan intervensi bisa ditawarkan dengan nilai yang lebih tinggi. Dalam kerangka expected utility, perilaku menyimpang akan tetap rasional jika risiko hukuman rendah dan sistem pengawasan lemah. Lihat saja bagaimana praktik suap di kalangan advokat yang kerap sulit disentuh hukum, namun justru praktik suapnya semakin “gila-gilaan”.
Sebenarnya, pemerintah tinggal menyusun potongan-potongan puzzle yang telah lama tersedia. Kajian ilmiah tentang sistem peradilan (court system) telah banyak disusun oleh para akademisi. Tugas negara adalah menjadikannya sebagai kebijakan publik yang utuh dan sistematis, dengan tetap menempatkan integritas sebagai fondasi utama.
Pada akhirnya, hakim adalah agen, dan negara adalah principal. Gaji tinggi memang dapat mengurangi moral hazard, namun itu harus disertai dengan mekanisme monitoring serta sistem reward and punishment yang berjalan efektif. Tanpa itu, budaya hukum di kalangan hakim akan terus bertabrakan dengan nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi jiwanya.