Para Agen Pendidikan

P E N G A N T A R R E D A K S I
MEMBICARAKAN pendidikan sering kali berakhir pada serangkaian slogan yang indah. Guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa, ujung tombak perubahan, bahkan fondasi masa depan bangsa. Namun siapa sesungguhnya yang mempedulikan masa depan para guru itu sendiri, selain dalam pidato dan baliho peringatan?
Pertanyaan ini bergaung sejak lama, pada 1950-an, Menteri PPK (Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan) Moh. Yamin sudah mengeluhkan bahwa profesi guru adalah pekerjaan yang paling dimuliakan dalam kata namun paling lambat disentuh dalam kebijakan, sebuah ironi yang kemudian kembali mencuat pada demonstrasi guru di berbagai daerah pada 1970-an.
Ironi itu tak berubah hingga kini. Laporan Bank Dunia tahun 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen guru di Indonesia mengajar di sekolah dengan fasilitas minim, sementara survei Kemdikbud 2022 mencatat lebih dari 40 ribu guru honorer bergaji di bawah Rp500.000 per bulan. Kisah-kisah individual pun tak kalah memilukan, laporan media dari NTT menyoroti seorang guru honorer yang bertahun-tahun mengajar dengan gaji hanya Rp200.000 per bulan, dan di banyak daerah lain guru terpaksa merangkap pekerjaan sampingan demi bertahan hidup.
Semua fakta itu menegaskan satu hal yang seakan tak berubah sejak puluhan tahun lalu: slogan-slogan tentang kemuliaan profesi guru sering jauh lebih nyaring daripada perhatian nyata terhadap kesejahteraan mereka.
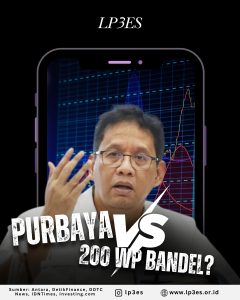
Kita mudah terpukau oleh bangunan-bangunan sekolah baru, kurikulum yang terus dirombak, atau jargon digitalisasi pembelajaran. Tetapi siapa yang menggerakkan semua itu? Siapa yang bersentuhan langsung dengan anak-anak, membentuk imajinasi dan kebiasaan berpikir mereka, lalu melanjutkan kerja keras itu dari pagi hingga petang? Siapa yang mengubah manusia kecil menjadi warga negara?
Jawabannya jelas: guru. Namun justru merekalah yang paling sering dilupakan dalam sistem pendidikan kita.
Ada semacam ironi historis yang terus berulang. Guru dipuji dalam kata-kata, tetapi dipinggirkan dalam kenyataan. Mereka ditempatkan sebagai aktor utama pendidikan, tetapi hanya sejauh mereka sanggup mengikuti tuntutan administrasi, target capaian, dan indikator-indikator evaluasi yang dirumuskan dari ruang birokrasi yang jauh dari kelas-kelas riil. Mereka adalah pekerja pengetahuan yang setiap hari diminta menghasilkan “produk pendidikan”, namun jarang diberi ruang menentukan bentuk dan arah pengetahuan itu sendiri.
Sejak awal industrialisasi pendidikan modern, pekerjaan guru berubah menjadi serangkaian tugas yang semakin teknis, semisal: mengisi platform, mengubah nilai menjadi angka, menyusun laporan yang tak pernah selesai. Mereka adalah labor pedagogis yang menggerakkan mesin pendidikan nasional, namun penghargaan terhadap mereka tetap diberikan melalui sistem upah yang kerap tidak mencerminkan beban mental, emosional, dan intelektual yang mereka emban.
Pantas saja, banyak guru merasa suara mereka tidak dianggap sebagai ahli pendidikan, sebab apa yang mereka hasilkan sering dibingkai bukan sebagai kerja intelektual, tetapi sebagai pelaksanaan kurikulum. Mereka bukan dianggap pemikir, padahal setiap hari mereka berhadapan dengan kompleksitas sosial yang tak pernah tertangkap oleh dokumen kebijakan. Mereka bukan sastrawan, padahal mereka adalah pembuka alfabet pertama bagi jutaan anak. Mereka bukan ilmuwan, padahal merekalah yang menyalakan penasaran pertama dalam diri murid. Mereka bukan psikolog, padahal setiap hari mereka menjadi sandaran bagi murid-murid yang membawa pulang beban sosial keluarganya ke ruang kelas.
Jika demikian, mungkinkah kita tiba-tiba “menaikkan derajat” mereka pada Hari Guru, dengan mengucapkan bahwa guru adalah pencipta peradaban? Klaim itu tentu mudah diucapkan, tetapi sulit diwujudkan tanpa mengubah suatu hal yang lebih mendasar, yaitu cara kita memandang kerja guru.

Kiranya, selama pandangan kita tentang guru masih berada dalam horizon lama, yang mana guru sebagai pelaksana, bukan perumus; guru sebagai tenaga kerja, bukan produsen kebudayaan, maka Hari Guru hanya akan menjadi perayaan seremonial yang tidak menyentuh akar persoalan. Sebab pendidikan hari ini masih terbagi secara tajam antara perancang kebijakan dan pelaksana lapangan, antara mereka yang mengatur arah dan mereka yang harus menanggung akibatnya.
Karena itu, melalui pengantar redaksi yang terbit pada 24 November ini, satu hari menjelang Hari Guru 25 November, kami menegaskan bahwa Hari Guru seharusnya tidak berhenti menjadi ritus tahunan.Ia perlu menjadi kesempatan untuk meninjau kembali relasi antara “kerja konkret” guru di ruang kelas dan “kerja abstrak” para pengambil keputusan. Bukan untuk meniadakan perbedaan, tetapi untuk memastikan bahwa suara guru—sebagai agen pendidikan yang sesungguhnya—menjadi bagian dari perumusan masa depan.
Hanya dengan cara demikian, kita dapat menciptakan masyarakat baru yang bukan hanya membutuhkan guru, tetapi juga mendengarkan mereka.
Redaksi Scholarium LP3ES




