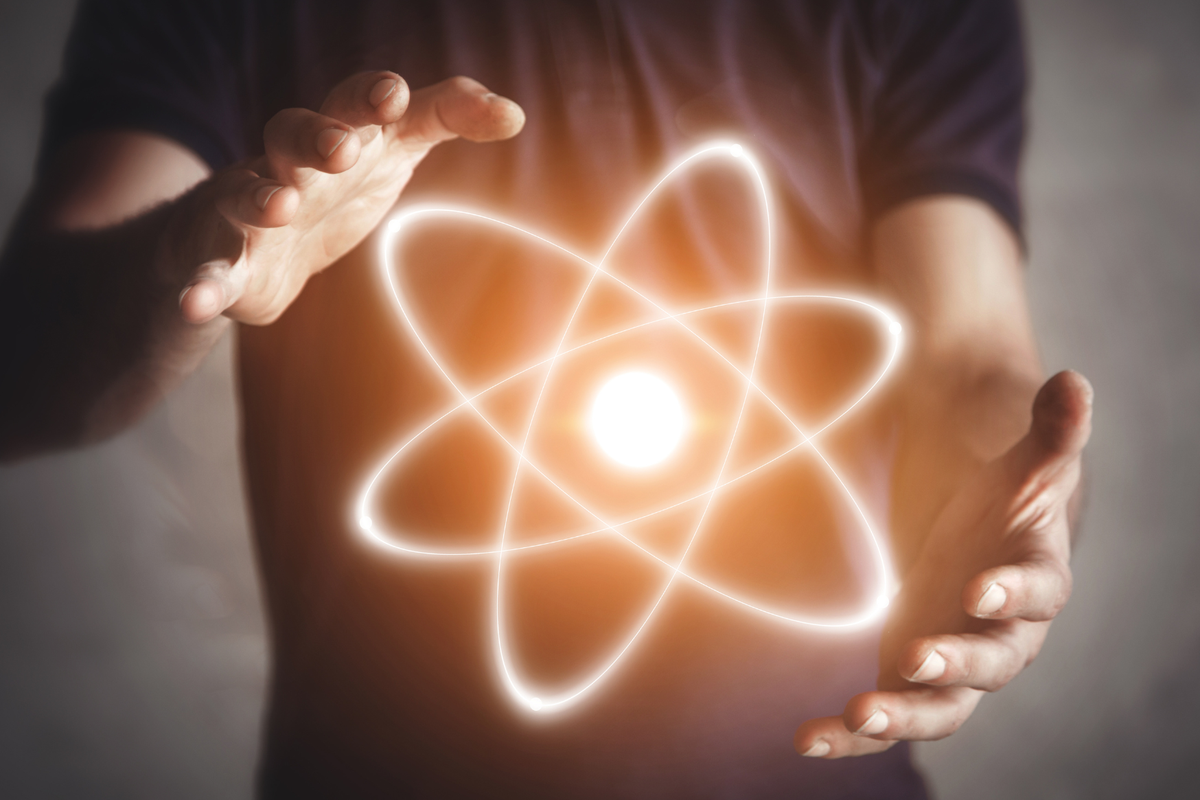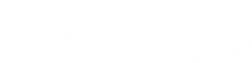Sejarah Berubah, Represi Berulang

Sejarah, bila ditatah oleh tangan kuasa, lebih menyerupai cermin retak: ia memantulkan citra yang disukai penguasa, sembari menenggelamkan luka yang tak ingin diingat. Maka bangsa ini pun berdiri di antara dua kebisuan: kebisuan para korban yang tak diakui, dan kebisuan para sejarawan yang dibeli oleh reputasi. (red.)
Pemerintah berdalih penulisan ulang sejarah diperlukan demi menciptakan harmoni sosial. Namun, harmoni yang dimaksud kerap direduksi menjadi sebatas tumbuhnya rasa cinta tanah air. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan revisi sejarah akan diarahkan ke citra positif namun tidak menguburkan sejarah lainnya.
Frasa ‘citra positif’ artinya mengandung kesan yang baik. Jika Masyarakat hari ini menganggap Orde Baru merupakan periode yang buruk. Artinya ada citra negatif dalam persepsi Masyarakat. Sehingga pengubahan ke arah citra positif secara tidak langsung akan merubah persepsi yang sebelumnya negatif menjadi positif.
Kekhawatiran publik pun wajar mencuat, mengingat revisi sejarah ini disinyalir sarat kepentingan politik kekuasaan. Jika kita analisis dalam wawancara singkatnya, Fadli Zon selaku otak daripada penulisan ulang sejarah, banyak menggunakan logika kelas sebagaimana yang di konsepkan Bourdieu. Sebagai contoh ia mengungkapkan bahwa yang mempunyai hak dalam menulis sejarah adalah para sejarawan, bukan aktivis. Bagi Bourdieu, kelas sosial terbentuk dan direproduksi melalui interaksi antara modal –baik ekonomi, sosial, budaya– dan habitus.
Dalam hal ini Fadli Zon menggunakan modal sosial, yaitu para sejarawan yang jumlahnya mencapai 113 hingga 120 orang sebagai jaringan hubungan sosial dan koneksi yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan kekuasaan. Sehingga ia mempunyai barisan depan yang kuat yaitu para sejarawan. Barisan ini menjadi semacam benteng legitimasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi wacana negara atas sejarah.

Bahaya Tafsir Tunggal
Konsekuensi penulisan ulang sejarah berpotensi menjadi tafsir tunggal atau berubah menjadi alat untuk mengaburkan sejarah yang tidak dituliskan oleh pemerintah. Sebab pola-pola tersebut pernah kita jumpai di Orde Baru. Semua orang bisa mengklaim dirinya sebagai sejarawan, tapi tidak semua orang mampu memahami metode penelitian sejarah. Sama seperti para militer dan polisi yang mengklaim bahwa dirinya paling Pancasilais, di sisi lain mereka menodongkan senjata ke kepala Mahasiswa dan Masyarakat.
Sehingga dalam wawancara interaktif dengan Fadli Zon, tidak terlihat titik temu landasan sebenarnya penulisan ulang sejarah. Sebab sejak awal wacana ini sudah dijegal dengan menerapkan logika kelas.Kita dibentuk oleh konstruksi sosial di mana kita hidup. Logika kekuasaan dari Indonesia merdeka sampai dengan hari ini nyaris sama, yaitu soal materi dan dinasti politik. Realitas pada akhirnya akan membentuk persepsi. Bukan persepsi yang seharusnya mengubah realitas.
Pierre Bourdieu masih dalam logika kelas, menyambung ungkapan di atas memperkenalkan habitus atau disposisi yang terinternalisasi, yang terbentuk dari pengalaman hidup dan interaksi dengan dunia sosial. Habitus dapat memengaruhi cara individu berpikir, merasa, dan bertindak, serta bagaimana mereka memahami dunia sosial.
Hal itu selaras dengan apa yang dilakukan pemerintah sampai dengan hari ini. Selalu memakai cara pandang bahwa mereka merupakan otoritas tertinggi dalam sebuah negara. Dalam arti administratif memang betul. Tetapi ketika semua dijalankan dengan cara pandang tersebut, hal itu justru berbahaya. Seperti yang dilakukan Mendagri soal empat pulau di Aceh: mengeluarkan peraturan yang berpotensi memecah belah. Terlalu dominan. Sifat keserakahannya selalu muncul — merasa yang paling tinggi.
Akhirnya kita menyadari bahwa kekuasaan merupakan bentuk kapitalisme simbolik tertinggi. Konsekuensi adalah absolute power. Kebenaran itu datang dari versi pemerintah, bukan dari aktivis atau lembaga swadaya masyarakat.

Kacamata Yurisprudensi
Mengubah sejarah artinya mengubah persepsi. Yurisprudensi tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai produk pemikiran, budaya, nilai, dan sejarah manusia. Dalam perspektif ini, hukum bukan hanya soal pasal-pasal, melainkan juga soal “mengapa” dan “bagaimana” hukum itu lahir dan berkembang.
Sejarah memiliki peran fundamental sebab hukum adalah produk sejarah manusia. Jika kita perhatikan, sistem hukum muncul sebagai respons terhadap realitas sosial dan politik zamannya. Sebagai contoh, hukum Romawi muncul dari kebutuhan mengatur imperium yang luas, hukum Islam lahir dari wahyu, tapi juga menyesuaikan dengan kondisi Arab abad ke-7; common law di Inggris berkembang dari keputusan-keputusan hakim selama ratusan tahun.
Artinya, sejarah membentuk nilai dan asas hukum. Prinsip-prinsip seperti keadilan, hak milik, keadilan prosedural, dan pembedaan antara hukum pidana dan perdata, semuanya tidak muncul begitu saja, tapi melalui pengalaman panjang peradaban yang membentuk gagasan tentang benar dan salah. Historical school of law, yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny, mengatakan: “Hukum itu tidak diciptakan secara tiba-tiba oleh negara atau penguasa, tetapi tumbuh secara organik dari kebiasaan, adat, dan kesadaran hukum masyarakat.” Artinya, sejarah dan kebudayaan suatu bangsa adalah sumber utama hukum.
Dalam filsafat hukum modern, tafsir hukum yang baik harus memahami konteks sejarah pembentukan hukum tersebut. Sebagai contoh, dalam hukum konstitusi menafsirkan UUD tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah lahirnya (misalnya, semangat kemerdekaan, trauma penjajahan, dan sebagainya). Dalam hukum Islam (fiqih), kita mengenal asbāb al-nuzūl (sebab turunnya ayat) dan konteks sosial Nabi Muhammad SAW sangat penting untuk memahami hukum syar’i.
Kita analogikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam sejarahnya, UU TPKS yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan lahir karena Indonesia dianggap telah darurat kekerasan seksual. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2012 kala itu, terdapat 4.336 kasus kekerasan seksual yang tercatat. Dari jumlah tersebut, 2.920 kasus terjadi di ranah publik/komunitas, dengan bentuk kekerasan yang paling banyak adalah perkosaan dan pencabulan. Artinya, kasus-kasus diatas akan menjadi bagian dari sejarah yang melatari lahirnya UU TPKS, sebuah upaya untuk memberantas kekerasan seksual yang kian merajalela.
Jika kita menggunakan logika pemerintah saat ini yang tidak mengakui pemerkosaan massal tahun 1998 sebagaimana diucapkan Fadli Zon, maka pemerintah seolah berusaha menghapus kasus-kasus memori masa lalu. Kemudian, apa yang kita ingat dari pembentukan UU TPKS? Maka, konsep yurisprudensi dan implementasi hukumnya juga akan bergeser. Pelaku bisa saja dihukum ringan, karena dianggap perbuatannya baru dan tidak pernah terjadi di masa lalu. Sehingga dapat diberlakukan alasan pemaaf yang mengakomodasi kondisi tersebut.
Akibatnya, pola-pola kekerasan seksual dalam sejarah masa lalu dapat berulang kembali atau diadopsi oleh rezim sekarang. Posisi Perempuan akan semakin terancam. Apa yang sudah diperjuangkan oleh teman-teman Perempuan sampai dengan hari ini seakan dihapus begitu saja oleh pemerintah. Karena pemerintah tidak mengakui jika dahulu ada kasus kekerasan seksual massal.
Sejarah bukan sekadar latar belakang hukum, tetapi bagian dari jiwa hukum itu sendiri. Hukum tidak bisa dilepaskan dari akar sejarahnya, karena dari sanalah nilai, norma, dan sistem hukum itu berasal. Maka hal itu juga akan berkorelasi dengan hukum yang ditafsirkan suatu saat. Sesuatu yang seharusnya salah bisa saja berubah menjadi seolah olah benar.
Tidak mengakui adanya pemerkosaan massal tahun 1998 seperti membuka luka lama kembali. Harapan korban akan munculnya keadilan, kini seperti dikubur hidup-hidup oleh kekuasaan yang sangat bengis. Perlindungan terhadap Perempuan harus terus ditingkatkan. Jangan sampai perempuan berada di posisi kelam sebagaimana yang telah diungkapkan dalam sejarah. Yang kini sejarah itu perlahan ingin dihapus oleh pemerintah.