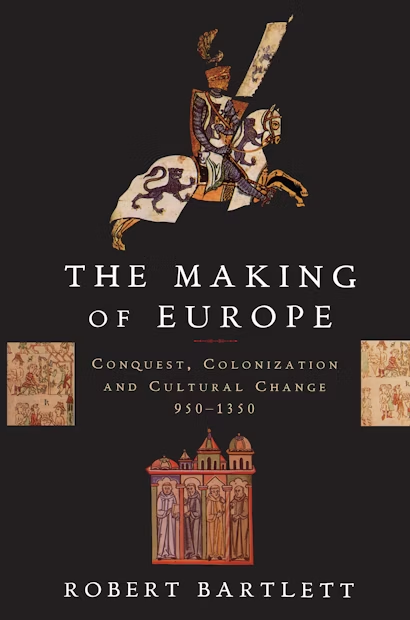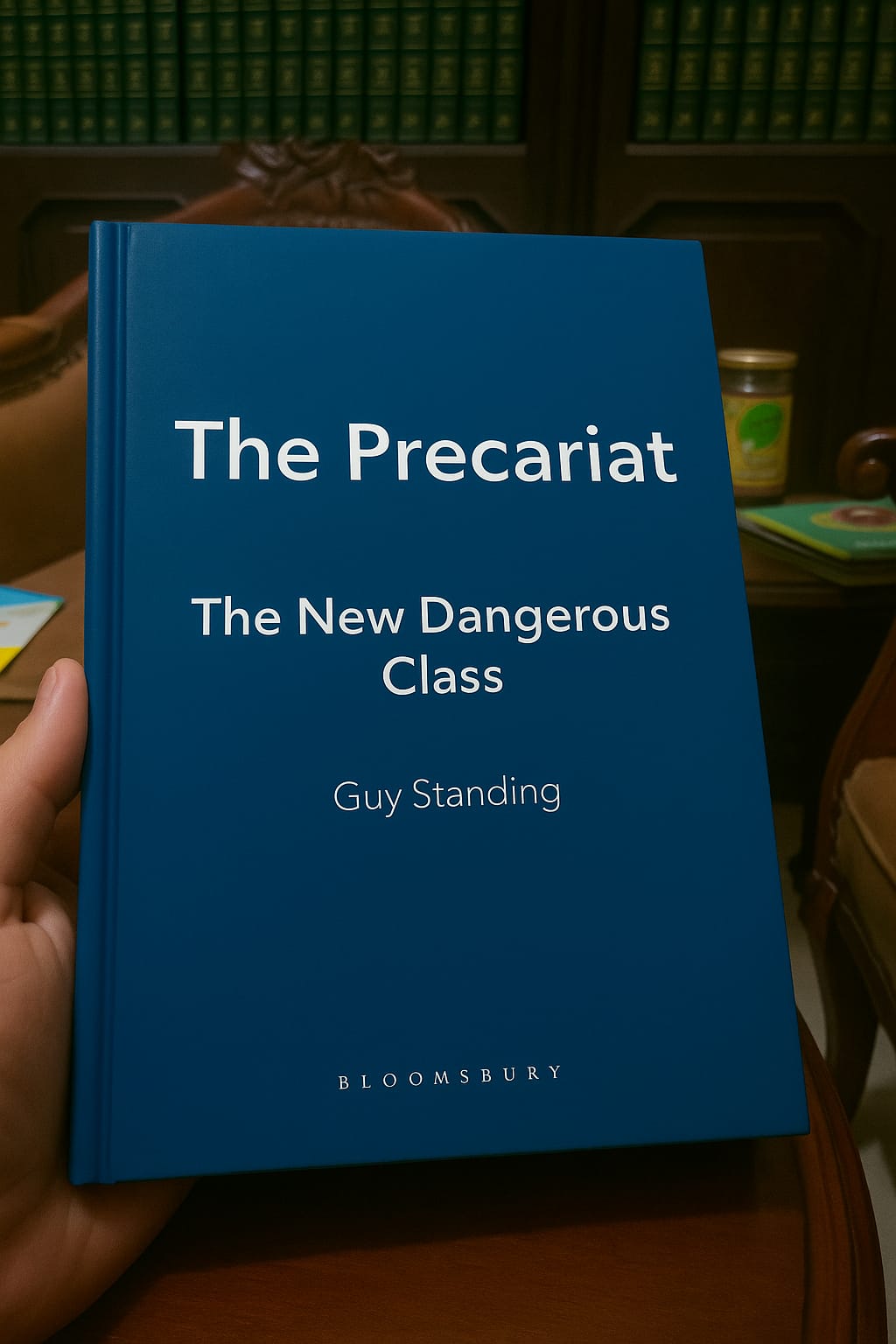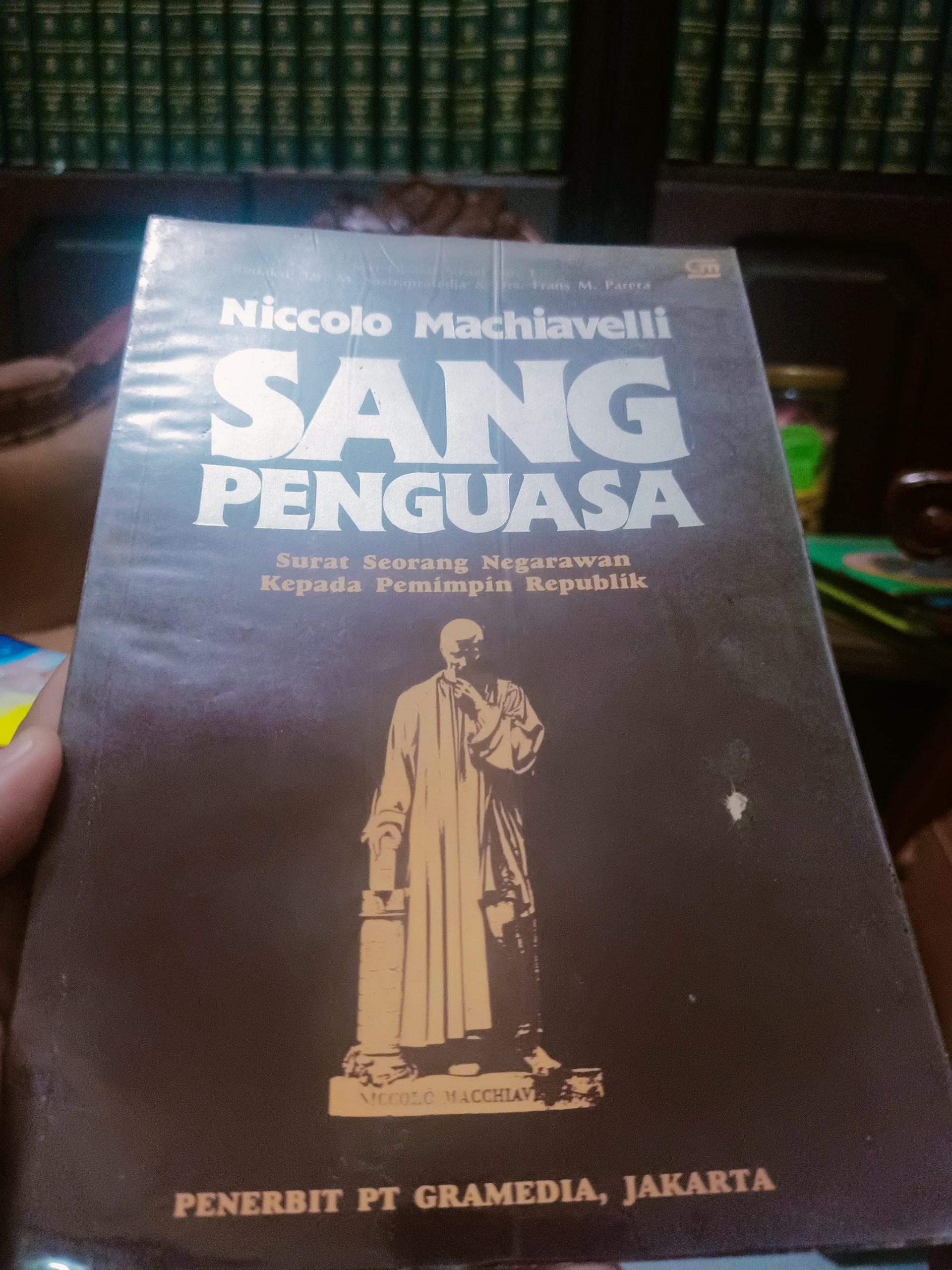Surakarta dalam Pusaran yang Bergerak

Judul: Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–1926
Penulis: Takashi Shiraishi
Penerbit: Pustaka Utama Grafiti (terjemahan bahasa Indonesia)
Tebal: xxviii + 504 halaman
Tahun Terbit: 1997 (cetakan pertama, edisi terjemahan); edisi asli bahasa Inggris: An Age in Motion (Cornell University Press, 1990)
Takashi Shiraishi, sejarawan kelahiran Jepang, menulis Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–1926 dengan laku telaten yang mendekati kerja seorang pemahat, bukan hanya pencatat. Disusun dari disertasinya di Cornell University dan pertama kali terbit dalam bahasa Inggris tahun 1990, buku ini lahir dari riset arsip selama lebih dari satu dekade di Den Haag, di perpustakaan nasional Jakarta, di pojok-pojok rak LIPI, dan lebih penting lagi: di celah antara ingatan dan diamnya dokumen resmi.
Terbit dalam terjemahan bahasa Indonesia oleh Hilmar Farid pada 1997, karya ini bukan semata-mata kronik organisasi politik bumiputra, melainkan pembacaan ulang atas kesadaran rakyat yang perlahan bergerak, membentuk diri, dan melepaskan diri dari kerangka kolonial dan historiografi negara.
Surakarta, sebuah kota di jantung Vorstenlanden (Tanah Kerajaan), dipilih bukan sebagai objek, melainkan sebagai panggung tempat elite keraton, kaum buruh, juru cetak, guru, mubaligh, santri, dan wartawan memainkan lakon sejarah dengan bahasa yang sedang mereka ciptakan sendiri.
Antara tahun 1912 hingga 1926, saat Hindia Belanda mencatat sekitar 60.000 buruh perkebunan di daerah ini dan ratusan surat kabar lokal mulai beredar dari tangan ke tangan, Shiraishi mencatat bukan hanya tindakan, tetapi cara berpikir para pelaku sejarah. Ia tidak hanya menulis sejarah, tetapi mendengar bagaimana rakyat mengartikulasikan zamannya yang mulai bergerak.

Menggugat Kategori Sejarah
Di tangan penulisnya, sejarah tidak sekadar jejak-jejak yang ditata berdasarkan kemenangan akhir, melainkan ruang konflik tafsir yang belum selesai. Buku ini mengambil jarak dari cerita besar tentang “nasionalisme yang menemukan dirinya”, sebuah narasi yang biasanya dimulai dari Boedi Oetomo (1908), lalu bertahap menanjak menuju Sumpah Pemuda (1928) dan proklamasi kemerdekaan.
Yang dilakukan Shiraishi adalah membongkar kerangka itu, menyelip masuk ke retakan-retakan di antara arsip negara dan pidato resmi. Ia menunjukkan bahwa pergerakan rakyat pada dasarnya tidak tunggal, tidak selalu menuju satu nama: Indonesia.
Surakarta, antara 1912 sampai 1926, bukan satu arus sejarah, melainkan pusaran. Dalam pusaran itu, Islam, sosialisme, komunisme, dan nasionalisme tidak berdiri sebagai kutub-kutub yang berjarak, tetapi saling bertaut, saling berebut tubuh rakyat, saling berebut bahasa.
Historiografi kolonial –yang diwarisi dengan sedikit modifikasi oleh narasi pascakemerdekaan– telah sejak lama mengkategorikan gerakan dalam kotak-kotak: SI (Sarekat Islam) untuk Islam, PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk komunis, BU (Budi Utomo) untuk nasionalis.
Buku ini menolak klasifikasi beku itu. Sebaliknya, ia membuka kemungkinan membaca pergerakan sebagai proses penyemaian, di mana bahasa politik belum mapan, identitas belum membatu, dan aktor-aktornya belum merasa menjadi “pendahulu”.
Pekerjaan utama buku ini, dan sekaligus keberaniannya, adalah mempertanyakan mengapa sejarah pergerakan rakyat begitu tergoda untuk disederhanakan ke dalam tiga kotak: nasionalisme, Islam, dan komunisme.
Penulisnya mencurigai bahwa klasifikasi ini bukan berasal dari rakyat yang bergerak, melainkan dari negara yang mencatat. Dalam penelusurannya terhadap arsip kolonial, Shiraishi menemukan bahwa pengarsipan atas gerakan selalu berpijak pada dua sistem klasifikasi yang dibentuk oleh negara Hindia Belanda, yaitu klasifikasi rasial (Eropa, Timur Asing, Bumiputra), dan klasifikasi organisasi (partai, serikat, perhimpunan).
Ketika historiografi Indonesia pascakemerdekaan mengambil alih arsip ini, pengklasifikasian itu diganti secara nominal, dari “Inlander” menjadi “Indonesia”, dari “gerakan bumiputra” menjadi “kebangkitan nasional”, tetapi kerangka berpikirnya tetap.
Dengan memakai istilah yang lebih akrab bagi republik modern, sejarah kemudian menyamakan SI dengan gerakan Islam, PKI dengan komunis, BU dengan nasionalis, dan menjadikan ketiganya sebagai fondasi resmi negara.
Buku ini menggugat kemapanan itu. Ia menunjukkan bahwa para pelaku pergerakan pada dasarnya tidak bekerja dalam batas-batas itu. Mereka bergerak sebagai individu, menyusun makna dalam kata-kata mereka sendiri, dan baru pada pertengahan dekade 1920-an organisasi mulai mengambil alih suara mereka.
Dalam lanskap sebelum partai mendisiplinkan wacana, yang muncul justru keragaman tafsir: seorang mubalig seperti Misbach bisa menjadi simpatisan komunis, seorang penulis babad bisa membongkar feodalisme, seorang ningrat bisa mengorganisasi buruh. Mereka adalah para “pembelot kategori”, dan sejarah, kata buku ini, sebaiknya dibaca dari suara-suara mereka.

Surakarta, Panggung Zaman Bergerak
Surakarta bukan sekadar latar bagi pergerakan, melainkan simpul tempat seluruh ketegangan kolonial, feodal, dan modern bertemu. Pada dekade 1910-an hingga 1920-an, kota ini menampung tidak hanya dua istana (Kasunanan dan Mangkunegaran), tetapi juga kantor Residen Belanda, pusat garnisun kolonial, dan jaringan dagang Tionghoa yang kuat.
Surakarta adalah kota para pangeran, para bekel, para pedagang batik, dan para buruh cetak. Dalam wilayah administratif Karesidenan Surakarta yang mencakup sekitar 3.360 km², tercatat lebih dari 1,3 juta penduduk pada 1920, dengan lebih dari 134.000 tinggal di kota.
Komposisi sosialnya mencerminkan kepadatan lapisan kekuasaan: sekitar 5.000 orang Eropa dan Indo-Eropa, 14.000 Tionghoa, dan hampir seluruhnya tinggal berdempetan di dalam kota bersama ribuan buruh pabrik, santri pesantren, guru sekolah bumiputra, hingga abdi dalem.
Dengan jaringan kereta api yang dibangun sejak 1870-an dan jalur trem yang mencapai Boyolali dan Klaten, Surakarta menjadi poros logistik penting bagi distribusi gula dan batik. Sekitar tahun 1910, lebih dari 300.000 bau tanah (satuan ukuran tanah tradisional di Jawa pada masa kolonial) di wilayah ini disewakan kepada perkebunan Eropa, terutama untuk komoditas ekspor seperti tebu dan tembakau.
Ini menghasilkan dua hal bersamaan, intensifikasi eksploitasi tenaga kerja, dan munculnya komunitas buruh tani yang semakin sadar akan posisinya. Di kota ini pula, pada tahun 1912, Sarekat Islam cabang Surakarta dibentuk dan menjadi salah satu yang paling aktif, dengan ribuan anggota yang tersebar dari kampung ke kampung.
Di sinilah Shiraishi memusatkan pengamatannya. Ia tidak datang untuk menyusun kronologi tokoh besar, tetapi menyusuri lorong-lorong suara yang bersilang, antara bahasa abangan dan putihan, antara rapat umum dan khutbah Jumat, antara surat kabar rakyat dan lagu-lagu protes yang dinyanyikan para tukang becak dan buruh cetak.
Terdapat dua nama penggerak yang prominan dalam pembahasan Shiraishi, yaitu Marco Kartodikromo dan Haji Mohammad Misbach.
Marco Kartodikromo bukan hanya tokoh, melainkan ruang cermin tempat rakyat melihat dirinya berbicara. Ia lahir dari tubuh sosial baru, seorang pribumi dari kelas bawah yang bekerja di perkeretaapian, lalu menulis, mengedit, dan menyerang.
Dalam tulisannya, dunia kolonial dibongkar dengan satire, ejekan, dan sindiran yang menyusup ke celah sistem yang terlalu serius untuk menyadari bahwa ia sedang ditertawakan. Marco menulis dalam bahasa Melayu Rendah, tetapi mencampurkannya dengan gaya surat kabar, babad, hingga roman.
Mas Marco, sapaan akrab nya, menjadi pemimpin redaksi Doenia Bergerak, surat kabar yang hidup singkat namun mengguncang. Dalam satu edisi tahun 1915, Marco menyindir bangsawan Jawa sebagai “penjaga kuburan Mataram” dan menulis tentang buruh dan kuli sebagai “bangsa yang ditelantarkan sejarah.” Ia ditangkap, dipenjara, dibebaskan, lalu ditangkap lagi. Namun, dalam dunia yang dikungkung oleh birokrasi kolonial dan feodalisme lokal, bahasa Marco menyebar lebih cepat daripada peluru dan lebih tajam dari pidato-pidato resmi.
Shiraishi membaca Marco bukan sebagai wartawan radikal semata, melainkan sebagai penulis babadan modern, yang menyusun kembali sejarah dari bawah. Di tangan Marco, perlawanan bukan sekadar gerakan politik, tapi penciptaan ruang simbolik: siapa yang boleh bicara, dengan bahasa siapa, dan untuk siapa sejarah ditulis.
Dalam kota Surakarta yang penuh tanda-tanda kekuasaan kolonial, dari Benteng Vastenburg hingga kantor Residen, Marco menanam benih otonomi dalam hal yang tampak sepele: pilihan kata, struktur kalimat, judul kolom. Di sini, politik dimulai bukan dari kongres, tapi dari ejaan.
Haji Mohammad Misbach adalah teka-teki yang tak kunjung selesai didefinisikan. Ia menulis traktat tentang ijtihad, berkhotbah di masjid Kauman, sekaligus menerbitkan Medan Moeslimin, surat kabar yang memuat artikel bertajuk “Islamisme dan Komunisme.”
Bagi banyak orang pada waktu itu, istilah itu sendiri sudah merupakan pelanggaran. Namun Misbach, yang berkain sarung dan bersorban, dengan tenang membongkar dikotomi antara agama dan revolusi. Ia menyebut kaum kapitalis sebagai “musuh Allah” dan melihat pemogokan buruh sebagai bentuk amar ma’ruf nahi munkar dalam praktik.
Dalam kampanye menentang pajak tanah, ia memimpin petani Klaten dan Karanganyar, membawa mereka bukan hanya dengan ajaran, tapi juga dengan logika produksi. Di hadapan para petani penggarap yang dihimpit sewa tanah dan upah kuli kontrak, Misbach tak menawarkan surga di akhirat, melainkan keadilan dalam distribusi hasil tani.
Pada 1918, ia ikut mendirikan Sarekat Abangan, sebuah organisasi yang menampung mereka yang tak cocok dengan garis elite Sarekat Islam pusat. Shiraishi membaca Misbach sebagai figur yang melampaui kotak ideologi; ia bukan sekadar Islam yang cenderung ke kiri, atau komunis yang kebetulan saleh, melainkan produk zaman yang membuat kategori ideologis itu sendiri rapuh.
Dalam penangkapannya tahun 1923 dan pengasingannya ke Manokwari, Shiraishi melihat satu babak penting dari hilangnya suara-suara silang ini dari panggung sejarah. Misbach dibuang bukan karena ia Islam atau komunis, tetapi karena ia mengaburkan batas yang ingin dibuat tegas oleh negara kolonial: antara masjid dan rapat umum, antara khutbah dan agitasi, antara takdir dan sejarah.

Babad Baru Rakyat
Ketika dekade 1920-an memasuki pertengahannya, yang dulu berupa gerakan spontan, penuh silang suara dan improvisasi, perlahan mulai dipadatkan menjadi garis-garis partai. Rakyat yang sebelumnya berbicara sebagai individu, melalui tulisan tangan, pamflet, khutbah, atau rapat kampung, kini diajak –atau didisiplinkan– untuk berbicara melalui organisasi: dengan ranting, kongres, dan keputusan pusat.
Sarekat Islam pecah menjadi dua, Centraal Sarekat Islam (CSI) yang loyal kepada Tjokroaminoto di satu sisi, dan mereka yang bergabung dengan kaum komunis di sisi lain. Pada tahun 1920, Komite PKI Surakarta dibentuk, dan dalam waktu dua tahun, organisasi ini telah memiliki jaringan serikat buruh, pemuda, dan petani yang masif, dengan disiplin partijtucht, kesetiaan garis partai yang tak boleh ditawar.
Gagalnya pemogokan umum PFB (Personeel Fabriek Bond) tahun 1923 menandai batas antara zaman mogok yang penuh agitasi dari bawah dan masuknya rezim perintah yang dikirim dari pusat.
Dalam fase ini, suara rakyat mulai diproses dalam struktur, dan kata-kata yang dulunya liar dan plural mulai disaring menjadi slogan: “hidup buruh!”, “turunkan pajak!”, “bubarkan feodalisme!”. Di Surakarta, Sarekat Ra’jat dan PKI menjadi dua mesin besar yang bekerja untuk menggalang massa, namun justru dalam kemegahan jumlah itulah paradoks baru muncul: rakyat dikonsolidasi, tapi kehilangan spontanitas; gerakan diperluas, tapi makna dipadatkan.
Shiraishi tidak menolak pentingnya organisasi, tetapi ia menggarisbawahi harga yang harus dibayar: ruang artikulasi yang lentur dan liar dari masa awal pergerakan kini dibingkai dalam format ideologi. Di sinilah buku ini tidak nostalgik, melainkan kritis: bahwa dalam proses menyejarah, sesuatu selalu dikorbankan, dalam hal ini, kebebasan rakyat untuk bicara dengan bahasa sendiri.
Pemberontakan tahun 1926 bukan klimaks, melainkan epilog yang getir. Di Surakarta, pemberontakan tidak pecah seperti di Banten dan Sumatera Barat, namun aparat kolonial mencium gelagatnya dalam percakapan yang bergerak cepat di pasar-pasar, dalam rapat yang tiba-tiba dibatalkan, dan dalam nama-nama yang mendadak hilang dari alamat mereka.
Dalam kurun singkat antara akhir 1925 hingga awal 1927, negara Hindia Belanda melakukan operasi penyisiran besar-besaran. Surat kabar dibredel, tokoh-tokoh Sarekat Ra’jat ditangkap, dan lebih dari 13.000 orang dicurigai terlibat jaringan subversif.
Di Surakarta sendiri, puluhan aktivis dibuang tanpa pengadilan ke Boven Digoel, sebuah hutan rawa di Papua yang dijadikan laboratorium pengasingan bagi tubuh-tubuh yang dianggap mengandung virus politik.
Di sana, yang tersisa bukan lagi agitasi, melainkan keheningan. Dalam bab terakhir bukunya, Shiraishi tidak merayakan perlawanan sebagai romantisme, tapi mengajak pembaca memandangi reruntuhan: apa yang hilang ketika sejarah ditutup oleh kekerasan negara. Ia tidak menulis tentang kegagalan, tetapi tentang penghilangan.
Yang hilang bukan hanya tokoh atau organisasi, tapi kemungkinan. Kemungkinan bagi politik yang ditulis dengan bahasa rakyat, bukan bahasa negara. Kemungkinan bagi gerakan yang tidak didisiplinkan oleh ideologi, tetapi dibentuk dari kegelisahan hidup sehari-hari: tentang harga beras, sewa tanah, upah kuli, dan rasa malu karena tak mampu membeli baju baru saat Lebaran.

Membaca Zaman dari Bawah
Hari ini, ketika sejarah semakin sering dipanggil untuk mengukuhkan identitas dan legitimasi, Zaman Bergerak justru datang sebagai ajakan untuk meragukan kepastian. Buku ini tidak memberi jalan lurus dari “kebangkitan” menuju “kemerdekaan”, tetapi memperlihatkan jalan-jalan kecil, kadang buntu, kadang berbelok, yang dilalui oleh mereka yang tak tercatat dalam buku pelajaran: para buruh percetakan, pemogokan petani, tukang batik, guru HIS, pemuda Sarekat Islam, juru bicara serikat kereta api.
Istilah-istilah teknis yang diselipkan Shiraishi, seperti partijtucht (disiplin partai), ijtihad (penafsiran mandiri dalam Islam), kring (lingkaran organisasi lokal SI), bekel (pemegang hak lungguh atas tanah), dan vergadering (rapat umum), bukan sekadar terminologi, tetapi penanda struktur sosial yang membentuk lanskap pergerakan.
Tokoh-tokohnya bukan tokoh besar dalam versi negara, tetapi tokoh-tokoh yang melintasi batas: Marco Kartodikromo, penulis babad rakyat yang melawan dengan kata; Haji Misbach, mubalig radikal yang menyatukan Islam dan komunisme; Tjipto Mangoenkoesoemo, kesatria garda depan dari dunia priyayi yang membelot dari ketundukan; dan Semaoen, organisator pemogokan yang mengartikulasikan teori kelas dalam bahasa massa.
Buku ini menjadi penting bukan karena menyusun ulang masa lalu, tetapi karena memperingatkan masa kini: bahwa setiap bahasa politik yang mapan dulunya adalah bahasa yang dibentuk dalam perlawanan.
Di tengah gelombang simplifikasi politik hari ini, Zaman Bergerak mengingatkan bahwa rakyat tidak lahir dari klasifikasi negara, mereka membentuk dirinya dalam mogok, dalam serikat, dalam khutbah, dalam satir, dan dalam keinginan untuk bicara atas nama sendiri.
Maka membaca buku ini hari ini bukan sekadar menyambung sejarah, tetapi membuka kembali kemungkinan: bahwa politik bisa tumbuh dari bawah, dari keragaman suara, dan dari perlawanan terhadap kategori yang membatasi.