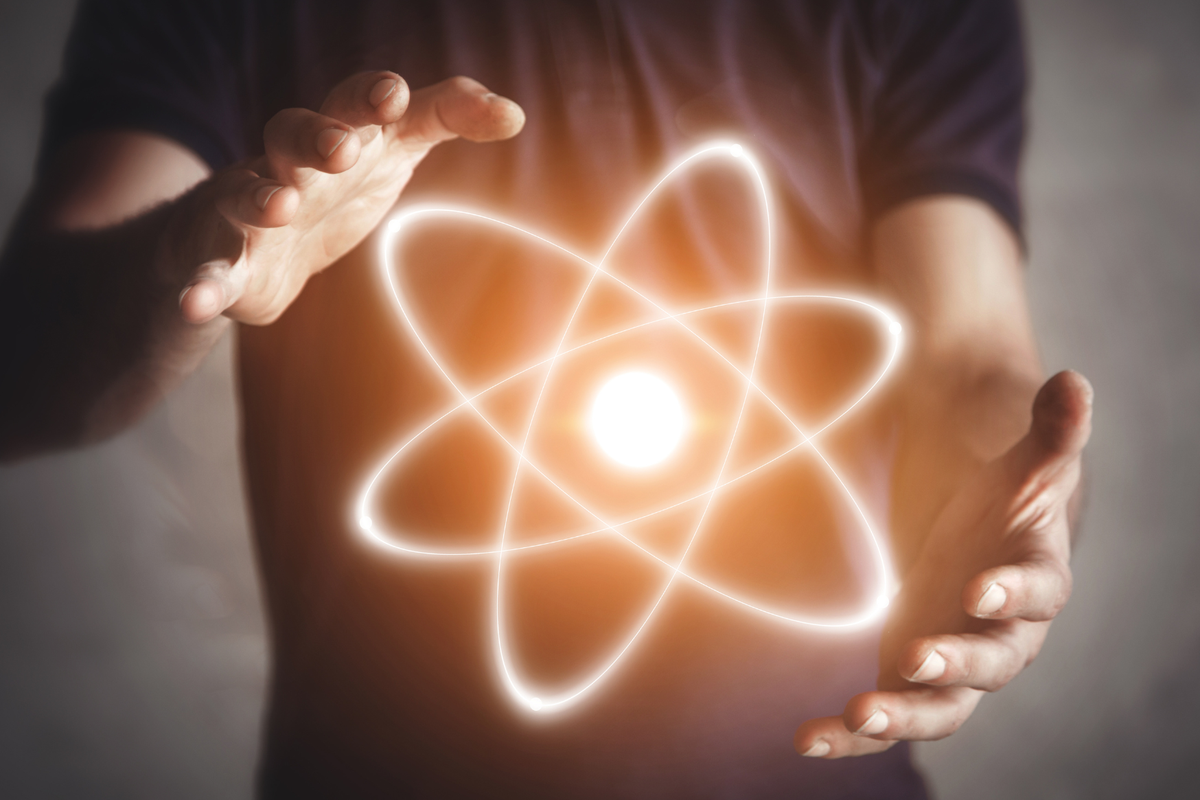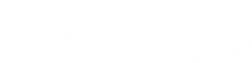Topeng Demokrasi Wajah Totaliter

Ada saat ketika demokrasi hanya tinggal topeng, dan di baliknya wajah lama yang hendak kita lupakan justru menampakkan diri kembali. Aksi yang seharusnya menjadi pesta wacana berubah jadi iring-iringan duka. Buku-buku kembali dianggap berbahaya, kata-kata ditakuti lebih dari peluru, dan rakyat dididik untuk percaya bahwa kebebasan hanyalah hak istimewa yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Pertanyaannya: apakah kita sedang hidup dalam demokrasi yang meremajakan dirinya, atau dalam totalitarianisme yang belajar menyamar? (red.)
Demonstrasi yang berlangsung pada 25 Agustus–1 September 2025 meninggalkan tragedi dan luka mendalam. Di negara yang menyebut dirinya demokratis, protes—yang semestinya menjadi saluran aspirasi—justru berakhir dengan hilangnya nyawa sedikitnya 10 orang. Salah satunya, Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online, tewas setelah dilindas mobil rantis Brimob. Tragedi ini, dan korban-korban lainnya, sejatinya bisa dihindari andai para elite bersedia membuka telinga terhadap suara rakyat, dan aparat memahami bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara.
Namun, pemahaman mendasar itu kini seolah menjadi barang mewah. Menyikapi kebuntuan komunikasi, gerakan masyarakat sipil dengan tulus merumuskan “pekerjaan rumah” bagi pemerintah: daftar 17 + 8 tuntutan yang disusun agar mudah dipahami, bahkan oleh mereka yang enggan mendengar. Salah satu tuntutan yang ditujukan langsung kepada kepolisian adalah pembebasan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi berlangsung.
Sayangnya, “pekerjaan rumah” itu seolah ditulis dalam bahasa asing bagi aparat. Alih-alih berbenah, polisi justru melanjutkan tindakan sewenang-wenang. Usai demonstrasi mereda, sejumlah aktivis ditangkap, termasuk Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, pada 1 September 2025. Penangkapan juga menyasar Khariq Anwar, admin akun Instagram Aliansi Mahasiswa Penggugat, serta admin akun Bekasi Menggugat. Data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menampilkan gambaran lebih kelam: lebih dari 3.000 orang di 20 kota ditangkap selama periode demonstrasi, dan jumlah itu terus bertambah seiring polisi memburu “aktor intelektual” yang sesungguhnya imajiner.

Infografis 17+8 Tuntutan Rakyat. (Foto: @scholariumco)
Nostalgia yang Tak Diinginkan
Tindakan represif aparat membangkitkan kenangan buruk masa lalu, nostalgia pahit yang tak pernah bangsa ini harapkan kembali. Gelombang penangkapan aktivis hari ini menggema seperti peristiwa 1997–1998, ketika aktivis diculik, disiksa, dan dihilangkan paksa oleh negara. Nama-nama seperti Wiji Thukul, penyair yang sajak-sajaknya menjadi bahan bakar perlawanan, hingga kini tak pernah kembali. Ia tetap menjadi simbol abadi dari suara kritis yang dibungkam selamanya.
Nostalgia kelam itu kian nyata ketika polisi mempertontonkan drama penggeledahan apartemen Delpedro. Di antara barang-barang yang disita “untuk kepentingan penyidikan” terdapat tumpukan buku. Adegan ini sarat simbolisme busuk: seolah gagasan adalah ancaman, yang bisa menyeret pemiliknya ke penjara. Taktik semacam ini klasik bagi rezim otoriter di mana pun: jika ingin mengendalikan rakyat, kriminalkan pengetahuan mereka.

Demokrasi atau Totalitarianisme?
Ketika aktivis dilempari tuduhan “menghasut” dan dijebloskan ke sel, wajar jika ketakutan merayap di tengah masyarakat. Itu naluri manusia yang merindukan kebebasan. Situasi ini mengingatkan pada catatan Theodore Dalrymple dalam esainya The Wilder Shores of Marx. Saat mengunjungi Rumania di bawah rezim totaliter Ceaușescu, ia menulis bahwa bagi masyarakat di sana, “…bahkan kebebasan—yakni tidak dipenjara—merupakan bentuk kebebasan tertinggi yang dikenal pada waktu itu.” Perbedaannya yang paling menakutkan: Dalrymple menggambarkan negara totaliter yang terang-terangan, sementara kita mengalaminya di Indonesia—sebuah negara yang mengaku demokratis.
Pemerintah tampak sadar dan sistematis berusaha mengkerdilkan gerakan masyarakat sipil. Hal ini tercermin dari diksi Presiden Prabowo yang melabeli aksi massa sebagai “huru-hara,” menuduh “tidak mau Indonesia sejahtera,” hingga menyelipkan tuduhan makar dan terorisme. Narasi semacam ini, ketika datang dari kepala negara, menjadi legitimasi bagi kekerasan aparat di lapangan. Situasi kian parah ketika Presiden turut menyebarkan misinformasi, seperti klaim bahwa demonstrasi harus mengantongi “izin,” padahal undang-undang hanya mensyaratkan “pemberitahuan.”
Frank Furedi dalam On Tolerance (2011) menyebut praktik semacam ini sebagai rekayasa sosial: menyebarkan narasi dan sikap “benar” versi penguasa melalui elite dan para ahli, untuk “mendidik kembali” masyarakat. Sebuah pola klasik rezim totaliter, ironisnya kini terasa relevan di tengah realitas politik kita.

Kebebasan Semu dan Kontrol ala Penguasa
Di tengah kondisi sekarang, rakyat seolah memiliki kebebasan. Namun kebebasan itu hanyalah paradoks, ilusi yang dipelihara untuk menutupi kenyataan bahwa setiap jalur menuju keadilan dipersulit. Contohnya tampak dalam penangkapan aktivis Delpedro Marhaen. Ketika proses hukumnya dikritik karena sarat kejanggalan, Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra justru meminta tim hukumnya untuk “gentle.”
Pernyataan ini menjadi cerminan sempurna dari paradoks tersebut: warga diminta mengikuti aturan permainan yang sejak awal telah dilanggar oleh aparat negara. Rakyat dipaksa menerima satu-satunya opsi yang telah dipilihkan penguasa. Seolah-olah adil dan bebas di permukaan, tetapi menindas di dalam.
Rekayasa ini tidak hanya berlangsung di ruang pengadilan, tetapi juga di ruang opini publik. Instrumen utamanya adalah pengerahan buzzer (pendengung) dan influencer (pemengaruh) untuk mendiskreditkan perjuangan masyarakat sipil. Meski kerap bekerja untuk tujuan serupa, keduanya beroperasi dengan cara berbeda: influencer memanfaatkan identitas asli dan popularitasnya untuk membangun audiens, sementara buzzer bergerak lewat akun anonim, menyebarkan narasi pesanan tanpa tanggung jawab.
Praktik ini makin nyata ketika figur publik seperti Jerome Polin mengungkap tawaran ratusan juta rupiah untuk menjadi pemengaruh pemerintah, mempromosikan “ajakan damai” yang sejatinya ditujukan untuk meredam kritik. Pada akhirnya, baik buzzer maupun influencer mengemban misi yang sama: membanjiri ruang digital dengan narasi alternatif, serangan personal, dan disinformasi, semata-mata untuk mengaburkan substansi tuntutan rakyat.
Lalu, mengapa taktik ini begitu efektif? Mengapa selalu ada orang yang rela “dibayar murah” untuk menyerang sesama warganya? Di sinilah peran negara dalam mengontrol kondisi ekonomi bekerja. Theodore Dalrymple mengamati bahwa kelangkaan (scarcity) yang diciptakan secara sistemis membuat orang hanya fokus bertahan hidup. Ia menulis, “…kelangkaan itu juga berarti orang dapat dibujuk menjadi informan, memata-matai, dan mengkhianati satu sama lain dengan sangat murah, demi keuntungan material sepele.”
Inilah lahan subur perekrutan para pendengung. Ketika pekerjaan langka dan biaya hidup mencekik, bayaran kecil untuk menyebar propaganda tampak menggiurkan. Negara, secara langsung maupun tidak, menciptakan kelaparan agar rakyat mudah dikontrol—dan diadu domba.
Pada tingkat lebih dalam, tujuan kontrol bukanlah meyakinkan publik, melainkan menghinakannya. Dalrymple mencatat: “Tujuan propaganda bukanlah membujuk, apalagi memberi informasi, melainkan menghinakan—dengan tanpa henti menegaskan apa yang terang-terangan bohong. Rezim menunjukkan kekuasaannya dan mereduksi individu menjadi sesuatu yang tak berarti.”
Ketika kebohongan diulang terus-menerus hingga diterima sebagai kewajaran, perlawanan pun tampak sia-sia. Negara seolah berbisik: “Kami tahu ini bohong, kalian tahu ini bohong, tapi kalian tidak bisa berbuat apa-apa.”
Penutup
Pada akhirnya, kekerasan dan kontrol ala penguasa memaksa warga negara pada pilihan tragis yang oleh Dalrymple disebut sebagai kebebasan terbatas, dibeli dengan harga pengebirian moral. Siapa memilih diam akan hidup lebih tenang; siapa bersuara harus siap menanggung konsekuensinya.
Inilah tujuan akhir dari seluruh strategi ini, seperti diidentifikasi Hannah Arendt dalam The Origins of Totalitarianism (1951):
“Subjek ideal dari pemerintahan totaliter bukanlah seorang Nazi yang yakin atau seorang Komunis yang yakin, melainkan orang-orang bagi siapa perbedaan antara fakta dan fiksi, serta antara benar dan salah, sudah tidak ada lagi.”
Kekuasaan dengan mudah dapat memutarbalikkan fakta: perjuangan aktivis yang sejatinya membela kepentingan rakyat digambarkan sebagai tindakan anarkis yang merugikan. Segala instrumen dikerahkan, dari kekerasan, senjata, dan bilik penjara, hingga kucuran dana bagi para pendengung dan pemengaruh. Narasi yang sudah dibolak-balik selalu menguntungkan mereka yang memilih berpaling dari yang tertindas.
Negara yang menutup diri dari demokrasi akan melahirkan masyarakat yang apatis, bingung, dan kehilangan kompas moral. Itulah kemenangan terbesar bagi sebuah rezim yang anti-kritik. Dan di titik itulah perlawanan sejati harus dirawat: menjaga akal sehat, memelihara keberanian. Sebab semakin ditekan, semakin kuatlah alasan untuk melawan.