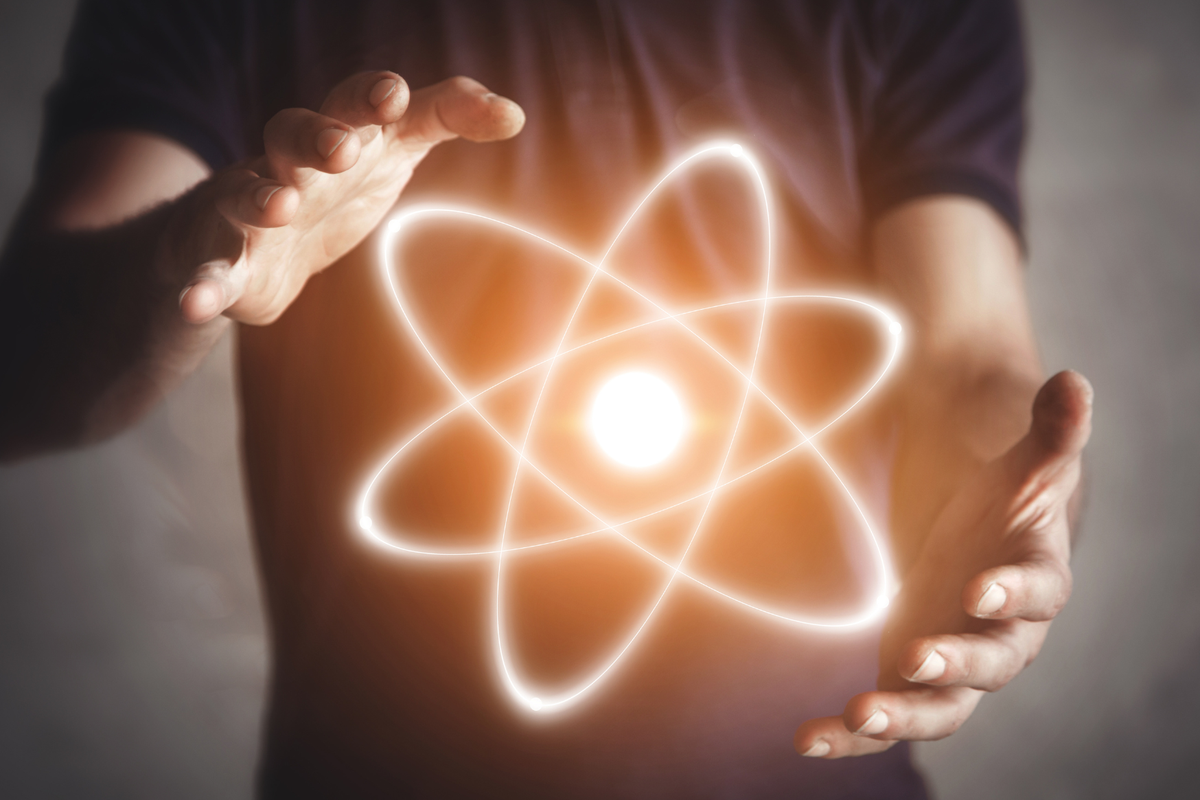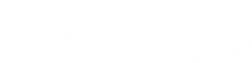Transformasi BUMN Karya: Efisiensi, Meminimalkan Risiko dan Harapan Dalam Pembangunan

Latar Belakang
Rencana pemerintah untuk melebur seluruh BUMN Karya, kelompok perusahaan pelat merah di sektor konstruksi, kini menjadi sorotan publik. Ketujuh perusahaan tersebut mencakup PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero). Pemerintah menargetkan peleburan ini menghasilkan tiga entitas atau klaster baru yang lebih solid dan efisien. Proses konsolidasi dijadwalkan rampung pada 2024–2025, sebagai bagian dari agenda restrukturisasi besar-besaran di sektor konstruksi milik negara.
Sebagai aktor utama dalam pembangunan infrastruktur nasional, dari jalan tol Trans Sumatra, jembatan, gedung, hingga proyek strategis lainnya, BUMN Karya pernah berjaya sebagai tulang punggung pembangunan Indonesia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, prestasi tersebut mulai dibayangi berbagai persoalan: utang yang menggunung, proyek yang mangkrak, hingga persaingan tidak sehat antar sesama BUMN. Di tengah situasi ini, pemerintah memandang konsolidasi atau merger sebagai jalan keluar untuk menyelamatkan industri konstruksi milik negara sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Lantas, mengapa pemerintah begitu ngotot mendorong peleburan BUMN Karya?

Alasan Dorong Merger BUMN Karya
Alasan pertama adalah untuk menghentikan persaingan tidak sehat antar sesama BUMN. Selama ini, proyek-proyek infrastruktur besar justru diperebutkan oleh perusahaan milik negara sendiri, yang saling berkompetisi sengit dalam tender. Akibatnya, sering terjadi “adu banting harga” yang pada akhirnya merugikan keuangan perusahaan. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyebutkan contoh nyata: Waskita Karya dan Hutama Karya yang sama-sama spesialis jalan tol kerap saling berebut proyek. Dengan konsolidasi, persaingan antar BUMN dapat ditekan, dan masing-masing entitas bisa fokus pada bidang spesialisasinya. Rencana klasterisasi ini pun telah dipetakan: Hutama Karya dan Waskita akan menangani jalan tol dan jalan raya; Wijaya Karya dan PP difokuskan pada proyek gedung serta konstruksi sipil umum; sementara Adhi Karya, bersama Brantas dan Nindya, diarahkan untuk menangani sektor air, properti, dan transportasi lainnya.
Alasan kedua adalah kebutuhan mendesak untuk melakukan restrukturisasi dan penyehatan finansial. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa menggabungkan tujuh BUMN Karya menjadi tiga entitas akan mempermudah upaya restrukturisasi utang dan membangun keahlian khusus di masing-masing perusahaan baru. Pemerintah menargetkan agar BUMN konstruksi ini dapat keluar dari jerat utang tanpa harus terus bergantung pada subsidi negara. Erick juga mengingatkan agar kegagalan PT Istaka Karya – BUMN yang bangkrut akibat utang proyek dan akhirnya merugikan banyak vendor swasta – tidak kembali terulang. Melalui proses merger, pemerintah berharap dapat mencegah kebangkrutan serupa pada BUMN Karya lainnya, sekaligus memastikan penyelesaian kewajiban terhadap subkontraktor dan mitra usaha kecil.
Alasan ketiga, merger diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. Penggabungan perusahaan akan memangkas biaya overhead, mulai dari kantor, struktur manajemen, hingga aset-aset yang tidak termanfaatkan. Proses bisnis pun dapat distandarisasi. Jika sebelumnya setiap BUMN memiliki struktur dan beban biaya masing-masing, tiga entitas baru ini diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya secara kolektif. Dengan skala yang lebih besar, mereka juga akan memiliki daya saing (competitive advantage) yang lebih kuat, termasuk dalam pembiayaan proyek serta kapasitas menangani konstruksi berskala besar, baik di dalam maupun luar negeri. Singkatnya, pemerintah memandang merger ini sebagai strategi bertahan hidup (survival strategy): membentuk BUMN konstruksi yang lebih ramping, efisien, terfokus, dan tangguh secara finansial.
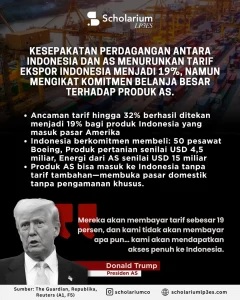
Tantangan BUMN Karya
Gagasan peleburan BUMN Karya tidak muncul tanpa sebab. Ia lahir dari tekanan berat yang saat ini tengah menghimpit para raksasa konstruksi milik negara tersebut. Tantangan utama adalah beban utang yang menggunung. Selama periode pembangunan infrastruktur besar-besaran, BUMN Karya agresif menarik pinjaman dari bank dan menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek jalan tol, jembatan, bandara, dan proyek strategis lainnya. Akibatnya, pada awal 2023, total liabilitas gabungan tujuh BUMN Karya mencapai sekitar Rp 287 triliun.
Beban utang terbesar ditanggung oleh Waskita Karya dengan lebih dari Rp 84 triliun, disusul Wijaya Karya (~Rp 56 triliun), Hutama Karya (~Rp 53 triliun), PT PP (~Rp 43 triliun), dan Adhi Karya (~Rp 30 triliun). Gambaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar BUMN Karya berada dalam kondisi over-leverage, yaitu menggunakan utang secara berlebihan untuk menopang aset mereka. Bahkan, rasio utang terhadap aset (Debt to Asset Ratio) per September 2023 berada di tingkat yang mengkhawatirkan: Waskita mencapai 87,1 persen, WIKA 83,5 persen, ADHI 77,2 persen, dan PTPP 74,5 persen. Artinya, sebagian besar aset perusahaan-perusahaan ini dibiayai utang.
Kondisi ini membuat ruang gerak finansial semakin sempit dan beban bunga utang kian menekan. Waskita Karya bahkan sempat gagal membayar kupon obligasi yang jatuh tempo pada 2023, dan dinyatakan default atas beberapa kewajiban jangka pendek. Jika tidak segera dilakukan penyehatan keuangan, utang-utang tersebut bisa menyeret BUMN Karya ke jurang kebangkrutan.
Tantangan berikutnya adalah kerugian operasional dan tekanan arus kas. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja keuangan BUMN Karya mengalami “pendarahan” akibat proyek dengan margin tipis, keterlambatan pembayaran, dan rendahnya efisiensi. Contohnya, Waskita Karya membukukan rugi bersih sebesar Rp 1,89 triliun pada 2022, yang kemudian melonjak menjadi Rp 3,77 triliun pada 2023. Sementara itu, Wijaya Karya yang sebelumnya mencatat laba Rp 117 miliar pada 2021, berbalik rugi Rp 59,6 miliar pada 2022, dan kembali anjlok menjadi Rp 5,8 triliun hanya dalam sembilan bulan di 2023 – atau naik lebih dari 200 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Adapun BUMN Karya yang lebih kecil seperti Adhi Karya dan PT PP masih mencetak laba tipis pada 2022 (masing-masing Rp 81 miliar dan Rp 272 miliar), namun jumlah itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan beban utang dan risiko proyek yang mereka tanggung. Bahkan, marjin keuntungan mereka terus tergerus. Sebagai contoh, meskipun pendapatan Wijaya Karya naik 17% pada 2022, beban pokok malah naik 19,6%, yang menunjukkan efisiensi operasional yang rendah. Proyek-proyek sering molor, mengalami pembengkakan biaya, dan pembayaran termin tertunda, memperparah arus kas.
Situasi ini diperparah oleh isu tata kelola. Salah satunya adalah kasus korupsi di manajemen Waskita Karya yang melibatkan rekayasa pembayaran proyek fiktif pada 2023. Skandal ini bukan hanya mengguncang internal perusahaan, tetapi juga menggerus kepercayaan publik dan investor. Kombinasi antara utang tinggi, kerugian besar, dan dugaan mismanajemen membuat BUMN Karya terjebak dalam kondisi keuangan yang sangat kritis.
Tantangan lainnya adalah tumpang tindih peran dan fragmentasi proyek. Tanpa koordinasi yang baik, BUMN Karya sering saling berebut proyek sejenis, bahkan cenderung saling “kanibal” pasar. Misalnya dalam proyek jalan tol, Waskita dan Hutama Karya sama-sama membangun jaringan tol di wilayah berbeda, namun dalam praktiknya mulai terjadi overlap kapasitas dan area kerja. Di sisi lain, dominasi BUMN Karya dalam tender proyek pemerintah menyebabkan kontraktor swasta makin tersingkir. “Selama ini setiap proyek antar BUMN saja, swasta nggak ada,” kata Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN.
Pola ini menciptakan ekosistem konstruksi yang tidak sehat. Negara terus menopang BUMN yang memenangkan proyek dengan harga di bawah nilai wajar, sementara swasta kesulitan tumbuh dan bersaing. Maka dari itu, tantangan besar yang perlu dijawab adalah mengakhiri fragmentasi, membangun kolaborasi, dan menciptakan sistem yang mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur secara lebih merata dan efisien.
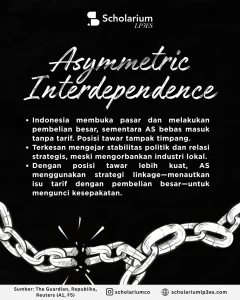
Dampak Potensial terhadap Industri Konstruksi dan Pembangunan Nasional
Jika proses peleburan BUMN Karya berhasil dijalankan dengan tepat, dampaknya bisa sangat signifikan bagi industri konstruksi nasional maupun agenda pembangunan negara. Dari sisi industri, penggabungan tujuh entitas menjadi dua hingga tiga perusahaan besar berpotensi menciptakan raksasa konstruksi nasional dengan total aset yang sangat besar. Pada tahun 2023, total aset gabungan BUMN Karya tercatat mencapai sekitar Rp 433 triliun, bahkan melampaui total aset holding pertambangan MIND ID. Artinya, pasca-merger, Indonesia akan memiliki champion nasional di sektor konstruksi dengan skala aset terbesar di dalam negeri. Perusahaan hasil merger ini diharapkan memiliki kapasitas modal dan operasional yang jauh lebih kuat, sehingga mampu menangani proyek-proyek strategis seperti jalan tol, bendungan, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tanpa terkendala pembiayaan. Dengan struktur keuangan yang lebih sehat, BUMN Karya hasil merger dapat lebih lincah mengeksekusi proyek tanpa tersandera oleh utang jangka pendek.
Selain itu, penggabungan ini memungkinkan adanya spesialisasi berdasarkan segmen proyek, yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Misalnya, klaster Hutama Karya, Waskita Karya akan difokuskan pada infrastruktur transportasi (jalan tol, jembatan, kereta api), klaster Wijaya Karya, PT PP akan berfokus pada pembangunan gedung, proyek EPC, dan potensi ekspansi luar negeri, sementara klaster Adhi Karya, Brantas Abipraya, Nindya Karya akan menangani proyek sumber daya air, properti, serta infrastruktur domestik lainnya. Dengan pembagian peran yang lebih jelas, tidak hanya terjadi pengurangan duplikasi proyek, tetapi juga peningkatan kompetensi masing-masing perusahaan. Bagi pengguna jasa, baik pemerintah maupun sektor swasta, hal ini akan memberikan keuntungan dalam bentuk proyek yang lebih cepat selesai dengan standar kualitas yang lebih terjaga.
Namun, rencana merger ini juga menyimpan sejumlah potensi dampak negatif yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah risiko pengurangan tenaga kerja akibat efisiensi operasional dan penghapusan posisi-posisi ganda. Ribuan pegawai bisa terdampak jika tidak ada skema transisi yang inklusif, seperti alih tugas, pensiun dini, atau penempatan ulang ke proyek lain. Di sisi lain, kontraktor swasta juga berpotensi terpinggirkan apabila entitas baru hasil merger menjadi terlalu dominan di pasar. Kekhawatiran ini tidak berlebihan, sebab setelah konsolidasi, hanya akan tersisa segelintir “super-BUMN” konstruksi yang bisa menguasai hampir semua proyek besar nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pasca-merger, mekanisme pasar tetap sehat dan kompetitif, misalnya dengan mendorong skema subcontracting kepada swasta atau memberikan ruang bagi kontraktor non-BUMN untuk memimpin proyek yang bukan bersifat strategis.
Dari perspektif pembangunan nasional, merger BUMN Karya dapat membawa dampak positif, tetapi hanya jika disertai dengan pembenahan manajemen dan struktur pendanaan. Proses penggabungan ini tidak akan berarti banyak tanpa restrukturisasi utang yang menyeluruh. Perusahaan baru harus memulai operasionalnya dengan neraca keuangan yang sehat. Dalam konteks ini, intervensi fiskal pemerintah sangat dibutuhkan, baik dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun melalui strategi asset recycling, yaitu menjual aset infrastruktur yang telah selesai dibangun ke investor (seperti INA), kemudian menggunakan dananya untuk melunasi utang. Langkah ini sudah mulai diterapkan, misalnya dalam upaya penyelamatan Waskita Karya yang tengah menjalani proses PKPU dan negosiasi dengan Kementerian Keuangan. Jika penyehatan ini berhasil, maka proyek-proyek strategis seperti Tol Trans Sumatra bisa diselesaikan sesuai target, dengan dukungan pendanaan yang lebih solid dari entitas hasil merger.
Namun demikian, perlu diingat bahwa merger bukanlah solusi instan. Penggabungan beberapa entitas besar seperti BUMN Karya adalah proses yang kompleks, membutuhkan waktu bertahun-tahun. Proses integrasi sistem, penyatuan budaya kerja, pengelolaan portofolio proyek, hingga harmonisasi beban utang memerlukan transisi yang hati-hati dan terencana. Pemerintah menargetkan roadmap konsolidasi ini berlangsung dalam rentang waktu 2024–2034, yang artinya manfaat penuh dari merger ini kemungkinan baru akan dirasakan dalam jangka menengah hingga panjang. Sementara itu, proyek infrastruktur tetap harus berjalan. Karena itu, pada tahap awal, dampak jangka pendek yang muncul bisa berupa penyesuaian organisasi internal, refocusing proyek, hingga penundaan aktivitas tertentu. Namun dalam jangka panjang, publik berharap merger ini mampu menciptakan BUMN konstruksi yang lebih kuat, efisien, profesional, dan berdaya saing tinggi, sehingga pembangunan nasional tidak lagi bergantung pada penyelamatan darurat dari negara, tetapi berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.
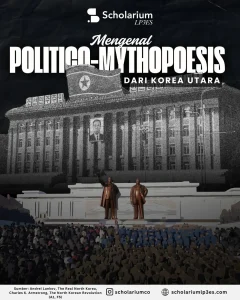
Rekomendasi Kebijakan dari Sudut Pandang Publik
Agar peleburan BUMN Karya benar-benar menghasilkan efisiensi finansial sekaligus berdampak positif dan adil bagi masyarakat, sejumlah rekomendasi kebijakan berikut perlu dipertimbangkan:
- Restrukturisasi Utang yang Transparan dan Tuntas
Pemerintah harus memastikan bahwa proses penyelesaian utang lama BUMN Karya dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Langkah-langkah seperti haircut utang, penjadwalan ulang, hingga konversi utang menjadi ekuitas dapat dipertimbangkan untuk meringankan beban finansial perusahaan. Namun demikian, beban restrukturisasi tidak seharusnya sepenuhnya ditanggung oleh negara. Kreditor, perbankan, dan investor obligasi juga perlu diajak berbagi beban melalui mekanisme negosiasi bunga atau perpanjangan tenor. Transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik serta mencegah terjadinya praktik yang tidak adil dalam penyelamatan keuangan BUMN.
- Pendampingan Manajemen dan Penguatan Tata Kelola
Pasca-merger, diperlukan penguatan sistem tata kelola dan pengawasan terhadap entitas baru. Kementerian BUMN perlu menunjuk manajemen profesional yang berintegritas, mengingat sejarah adanya kasus korupsi dan miskin tata kelola pada BUMN sebelumnya. Prinsip good corporate governance wajib ditegakkan, termasuk pelibatan figur independen dalam dewan komisaris serta pembentukan komite audit yang kuat. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa BUMN hasil merger akan dikelola lebih baik dan bertanggung jawab dibanding sebelumnya.
- Kolaborasi dengan Swasta dan Daerah
Agar merger tidak berujung pada terbentuknya monopoli BUMN di sektor konstruksi, pemerintah perlu mendorong kemitraan strategis dengan kontraktor swasta dan pemerintah daerah. Salah satu caranya adalah dengan membagi proyek besar menjadi paket-paket yang melibatkan subkontraktor swasta lokal, sehingga manfaat ekonominya lebih luas. Selain itu, BUMN hasil merger sebaiknya difokuskan pada proyek strategis yang kurang menarik bagi swasta (misalnya proyek jangka panjang atau bermargin rendah), sementara proyek komersial lainnya dapat diberikan kepada pelaku pasar. Model konsorsium antara BUMN, swasta, dan BUMD juga bisa menjadi solusi sinergis untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
- Perlindungan terhadap Pekerja dan Mitra Usaha
Proses merger harus memperhatikan aspek sosial dan perlindungan tenaga kerja. Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak akibat restrukturisasi. Sebaliknya, alih penugasan, pelatihan ulang, atau penempatan kembali ke proyek lain perlu difasilitasi bagi pegawai yang terdampak. Bagi vendor, subkontraktor, dan mitra usaha kecil lainnya, kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan harus dituntaskan sebelum merger efektif dijalankan, atau disusun skema pembayaran pasca-merger yang adil dan pasti. Efisiensi keuangan tidak boleh dibayar dengan mengorbankan kesejahteraan pekerja dan pengusaha kecil. Asas keadilan sosial harus menjadi prinsip utama dalam transformasi ini.
- Monitoring Kinerja Pasca-Merger
Pemerintah, bersama DPR dan publik, harus mengawasi kinerja entitas hasil merger secara ketat dan berkelanjutan. Diperlukan penetapan Key Performance Indicators (KPI) yang jelas, seperti penurunan rasio utang, ketepatan penyelesaian proyek, dan peningkatan laba. Target jangka pendek (1–2 tahun) dan jangka menengah (3–5 tahun) harus disusun secara realistis namun ambisius. Jika kinerja perusahaan pasca-merger tidak menunjukkan perbaikan atau bahkan kembali membebani APBN, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan restrukturisasi lanjutan. Sebaliknya, jika tercapai hasil positif, maka capaian tersebut harus dikomunikasikan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Penutup
Peleburan BUMN Karya sejatinya merupakan “operasi besar” yang ditujukan untuk menyembuhkan pasien-pasien industri konstruksi milik negara yang sedang mengalami krisis. Potensi keberhasilannya sangat nyata: struktur organisasi yang lebih ramping, manajemen keuangan yang lebih terkendali, serta kemampuan untuk mengerjakan proyek infrastruktur secara lebih efisien dan efektif. Namun, seperti operasi besar lainnya, keberhasilan ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang cermat, serta komitmen terhadap transparansi dan keadilan.
Jika dijalankan dengan benar, merger ini bisa menjadi titik balik besar bagi transformasi industri konstruksi Indonesia—tidak hanya menyelamatkan neraca keuangan BUMN, tetapi juga memperkuat landasan pembangunan nasional yang berkelanjutan, kompetitif, dan inklusif di masa depan.